
Senja hampir usai dan alam mulai beranjak gelap, serangga-serangga halus memenuhi udara di atas jalan yang berlubang itu, beberapa masuk di mataku dan terasa perih, laju sepeda motor sedikit kuperlambat. Desa Malik, nama kampung ini, sebuah desa di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sejak enam tahun lalu, kecamatan ini bergolak. Gerakan spontan petani melawan pencaplokan tanah mereka oleh PT Wira Mas Permai (PT WMP) belum juga usai. Meski perusahaan ini dalam aktivitasnya selalu mendapatkan pengawalan pasukan Brimob dari Kepolisian Resort Banggai, namun perlawanan petani, sekalipun skalanya kecil, masih terus berlangsung. Saat ini para petani mendapatkan sekutu alamiahnya: kaum buruh, persisnya buruh perkebunan yang hidupnya juga melarat.
***
PT Wira Mas Permai atau biasa disingkat PT WMP adalah anak perusahaan dari Kencana Agri Limited. Kencana Agri Limited adalah produsen minyak sawit mentah (CPO) dan inti minyak sawit mentah (CPKO) dengan perkebunan kelapa sawit di daerah strategis Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Perusahaan ini dipimpin oleh Mr. Henry Maknawi. Sampai 31 Desember 2009, luas perkebunan Kencana Agri Limited diperkirakan lebih dari 188.000 hektar dengan luas tanaman lebih dari 39.000 hektar, termasuk tanah di bawah program plasma. Sejak 25 Juli 2008, Kencana Agri Limited telah menjadi perusahaan go public dengan mencatatkan sahamnya di papan utama Bursa Efek Singapura.
Di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, PT WMP beroperasi sejak 2009 ketika mereka mengantongi Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 525.26/15/Disbun tetang Izin Lokasi seluas 17.500 Ha. Pada 2011, perusahaan ini mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan Nomor 525.26/1922/Disbun. Di tahun itu juga, perusahaan ini mengantongi sertifikat HGU Nomor 82/HGU/BPNRI/2011 dengan luas lahan 8.773,38 Ha.
***
Dengan mata masih perih, kuparkir sepeda motor di depan sebuah pondok berhalaman luas, tanpa pagar, dengan pohon nangka tegak menjulang sebagai penghias. Sekali saja saya memberi salam dan yang punya rumah segera keluar menemui, seorang lelaki berumur sekitar 40 tahun dan seorang perempuan sekitar 30 tahun, saya rasa mereka suami istri. Kujulurkan tangan, “Saya Budi Pak, Pak Agus kan?” Dia membenarkan. Sebelumnya, saya memang telah mendapatkan sedikit informasi tentang dia dari seorang kawan buruh perkebunan.
Saya pun dipersilakan masuk ke rumah berlantai tanah itu. Di dalam, ada dua kursi plastik dan sebuah meja plastik, di sebelahnya ada sebuah tempat tidur dari kayu. Dua anak laki-laki berbadan kurus berbaring di situ, sedikit malu-malu menatapku. Anak yang lebih tua segera mematikan televisi dan masuk kamar, mungkin karena kehadiranku. Rumah ini hanya memiliki satu kamar, saya menduga mereka berempat tidur dalam satu kamar.
Tanpa pengantar panjang, saya langsung menceritakan siapa saya dan apa maksud kedatangan saya. Tidak lama berselang, istrinya datang membawa dua gelas kopi. Saya hanya bergumam dalam hati, “orang yang hidup sangat sederhana begini, begitu menghormati tamu, mungkin saja ini sendok kopi dan gula terakhir dalam kaleng penyimpannya.” Sambil menikmati kopi yang agak manis buatan istrinya, kami mulai bercerita tentang perjuangannya mempertahankan tanah dari pencaplokan PT WMP. Tiba-tiba saja istrinya datang membawa nampan dari plastik, di atasnya ada bakul ukuran kecil berisi nasi dan sepiring ikan goreng serta sambal. Segera saja dia mempersilakan kami makan. Untuk kedua kalinya hati saya bergetar, “orang semiskin ini begitu memuliakan tamu,” kepala saya sedikit tertunduk. Setelah selesai makan, kami baru melanjutkan cerita.
Tiba Pertama Kalinya di Desa Malik
Pak Agus berasal dari Isimu, sebuah daerah di Provinsi Gorontalo. Sekitar tahun 1991, dia berangkat ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia (UMI), mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Dia bercita-cita menjadi guru madrasah. Namun, nasib berkata lain. Karena tidak punya cukup biaya, kuliahnya berakhir saat memasuki semester empat.
Karena tidak bisa lagi meneruskan kuliah, Pak Agus kemudian berpikir untuk pulang kampung. Sampai di kampung, dia mendapatkan informasi bahwa banyak keluarganya di daerah Paguyaman, Provinsi Gorontalo, sekarang pindah ke Desa Malik, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Tanpa berpikir panjang, Pak Agus lalu berangkat menuju Desa Malik, siapa tahu di daerah baru, dia mendapatkan peruntungan. Dan ternyata benar, di tempat baru ini, dia mendapatkan jodohnya.
Keluarga yang Terusir oleh Modal
Sanak keluarga Pak Agus semuanya berasal dari satu desa, yakni Desa Pilomonu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Memang ada kesamaan nama antara Kecamatan Bualemo di Kabupaten Banggai dengan Kabupaten Bualemo di Provinsi Gorontalo. Pasalnya, mayoritas penduduk Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, berasal dari wilayah Provinsi Gorontalo, sehingga wilayah baru yang mereka tempati diberi nama yang sama.
Keluarga besar Pak Agus sebenarnya pindah ke Desa Malik bukan karena keinginan sendiri. Tetapi karena di desa asalnya, mereka tidak mempunyai apa-apa lagi untuk bisa bertahan hidup. Awalnya mereka memiliki tanah yang luas dan subur di tempat asal. Kelapa dan jagung adalah tanaman andalan mereka. Namun, semua berakhir dengan hadirnya perusahaan perkebunan tebu.
Pada awalnya, mereka mengira perkebunan tebu akan membawa kesejahteraan. Menurut orang Gorontalo, tanaman tebu atau dalam bahasa Gorontalo disebut patodu merupakan salah satu simbol adat di limo lo pohalaa. Tebu merupakan lambang rezeki atau makanan kemakmuran. Tetapi di Paguyaman, dimana konsesi pertama pabrik gula dilakukan pada 1992, ribuan hektare tebu yang ditanam bukan lambang kemakmuran. Namun sebaliknya, lambang kesengsaraan dan pengusiran.
Dengan alasan itulah, bermodal biaya ganti rugi lahan yang sebetulnya tidak mencukupi, 175 Kepala Keluarga (KK) dengan ketua rombongan Pak Hamza Ahmad berangkat menuju
Desa Malik pada 1997 untuk mencoba peruntungan. Pada awalnya, mereka meminjam lahan masyarakat atau bagi yang masih punya simpanan uang, membeli lahan milik masyarakat lokal yang saat itu masih sangat murah. Mereka menggunakan lahan itu untuk berkebun, menanam tanaman bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Tanah Harapan
Pada 24 April 2000, Hamza Ahmad selaku ketua rombongan dengan surat pengantar kepala desa saat itu, mewakili 175 KK memohon kepada Bupati Banggai untuk mendapatkan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Pada 6 September 2000, keluar surat rekomendasi dari bupati yang menjelaskan bahwa Bupati Banggai merekomendasikan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 450 Ha yang terletak di Desa Malik.
Setelah mendapatkan surat rekomendasi itu, 175 KK tersebut segera membuka lahan. Namun, mereka hanya mampu membuka lahan seluas 125 Ha dan menanam berbagai macam tanaman serta mendirikan pondok di tengah ladang. Bagi mereka, lahan tersebut adalah tanah harapan, harapan untuk masa depan anak dan cucu. Mereka tidak punya pikiran lagi untuk meninggalkan Desa Malik. Mereka berkeyakinan di sinilah mereka akan hidup, membangun keluarga, dan tentu saja setelah mati, akan dikuburkan di sini.
PT Wira Mas Permai: Perusahaan Pencaplok Tanah
Selama setahun dari 2009 sampai 2010, PT WMP dibantu pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa aktif mensosialisasikan maksud dan tujuan keberadaan mereka. Mereka menyatakan keberadaan mereka adalah untuk bermitra dengan masyarakat dan petani. Mereka datang bukan hanya untuk membangun perkebunan mereka, namun juga untuk membangun kebun-kebun plasma milik masyarakat.
Janji pihak perusahaan yang saat itu diwakili oleh manajer perkebunan Lutfi Wibisono dan bagian humas perusahaan Faisal Badjarat, bahwa mereka akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat disambut gembira. Apalagi janji perusahaan juga dikuatkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Camat Bualemo Isnaeni Larekeng. Pembagian 80:20 adalah kata kunci yang ampuh hingga petani rela melepaskan lahan mereka untuk ditanami sawit, meski sampai saat ini, mereka tidak pernah mengerti apa arti pembagian 80:20 itu.
Keluarga besar Pak Agus juga melakukan hal yang sama. Mereka melepaskan 75 Ha lahan mereka dari 125 Ha yang telah mereka olah, untuk ditanami sawit sehingga lahan mereka yang tersisa hanya 50 Ha. Bahkan Pak Agus sendiri juga merasa senang, karena tanaman yang tumbuh di atas lahan mereka diganti rugi dengan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) yang jumlahnya sekitar Rp500.000-Rp1.000.000. Ternyata belakangan baru diketahui pembayaran GRTT adalah surat pelepasan hak atas tanah. Dalam waktu singkat, tanaman penduduk berubah menjadi sawit dan pondok-pondok petani berubah menjadi barak serta kantor perusahaan.
Tapi bukan hanya itu, lahan-lahan milik petani yang tidak dilepaskan pada praktiknya juga digusur dan ditanami sawit oleh perusahaan. Maka lengkaplah sudah, tidak ada satupun lahan yang tidak ditanami sawit. Petani sempat memprotes, namun pihak perusahaan menjelaskan bahwa semua yang tergusur adalah untuk plasma. Para petani pun hanya bisa diam tanpa pertanyaan lebih lanjut.
Sialnya, perusahaan yang masih berada dalam proses awal membangun kebun dan membutuhkan tenaga kerja relatif banyak, berhasil merekrut para petani menjadi buruh kebun (untuk pekerjaan pembenihan dan penanaman). Meski upahnya sangat rendah, yakni Rp35.000/hari, dengan resiko kecelakaan kerja cukup tinggi dan tanpa manajeman keselamatan kerja sama sekali, namun apa dikata, mereka butuh uang kontan untuk kebutuhan sehari-hari.
Setelah tiga tahun berselang, kebutuhan akan tenaga kerja semakin berkurang dan kebun plasma juga tidak pernah ada. Sampai sawit dipanen, tidak ada pembagian sepersen pun untuk masyarakat. Maka lengkaplah penderitaan mereka, mau bertani tanah tidak ada lagi, mau menjadi buruh juga tidak ada lagi yang menyewa tenaga mereka, mencari rotan atau damar pun sangat sulit, karena hutan telah hilang berganti sawit.
Pak Agus Memimpin Perlawanan
Dengan kondisi seperti itu, banyak keluarga Pak Agus mulai berpikir meninggalkan Desa Malik. Tanah harapan tidak ada lagi, bekerja sebagai buruh tidak ada yang menyewa dan kalau pun ada, upahnya tidak seberapa karena harus bersaing dengan petani-petani desa lain yang bernasib sama. Di Kecamatan Bualemo, memang bayak petani kehilangan tanah, bahkan tanah-tanah transmigrasi yang bersertifikat, habis dicaplok oleh perusahaan. Kalaupun ada tanah yang tersisa, cuma lahan-lahan sempit. Dengan kurangnya modal dan teknologi, hasil bertani tidak bisa lagi diharapkan untuk menjamin hidup lebih layak.
Keluarga besar Pak Agus yang semula berjumlah 175 KK, kini tersisa 47 KK, kebanyakan telah pergi mencari tempat lain untuk hidup. Menurut Pak Agus, situasi ini jelas adalah pengusiran dan dia tidak ingin keluarganya yang tersisa kembali terusir seperti di Paguyaman. “Tanah-tanah harus diambil kembali, kalau tidak, kita tidak punya harga diri sebagai manusia,” kata Pak Agus. Ia juga menyatakan, “tanah-tanah itu adalah hak kami, dan dirampas seenaknya, mempertahankan tanah adalah jihad dan kalau toh harus mati kita mati syahid.” Kata-kata lugas dan tegas yang mengalir dari mulutnya membuat saya merinding.
Karena itu, pada tahun 2013, Pak Agus memimpin keluarganya yang tersisa untuk menduduki lahan-lahan yang dikuasai perusahaan. Tanaman sawit dibakar dan tanah kembali ditanami jangung, kedelai dan wijen. Pondok-pondok juga kembali didirikan. Total luas lahan yang mereka reklaim adalah 43,5 Ha dari 55 Ha yang tidak diberikan GRTT.
Menanggapi tindakan pengambilalihan tanah oleh petani itu, pihak perusahaan langsung mendatangkan aparat kepolisian (Brimob) dengan peralatan penuh. Bukan hanya itu, preman-preman bayaran perusahaan setiap harinya datang meneror petani. Namun, para petani tidak bergeming. Mereka tetap menduduki dan mengolah lahan tersebut sampai saat ini. Seperti kata pak Agus, “apa yang kami lakukan ini adalah jihad, kalau toh darah saya akan tertumpah, maka saya tidak akan menyesal sama sekali dan Insya Allah saya mati sebagai syahid”.
***
Tidak terasa waktu telah menunjukan pukul 23.45 WITA. Pembicaraan yang menguras emosi ini terpaksa diakhiri. Saya pamit pulang dan berjanji akan datang lagi. Kami bersalaman dan Pak Agus sedikit menundukan tubuhnya. Saat itu, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. (Budi Siluet)
***
Tulisan ini pernah dimuat di majalah Seputar Rakyat, Edisi 1 Tahun 2016, yang diterbitkan Yayasan Tanah Merdeka (YTM). Dimuat ulang di sini untuk tujuan pendidikan.
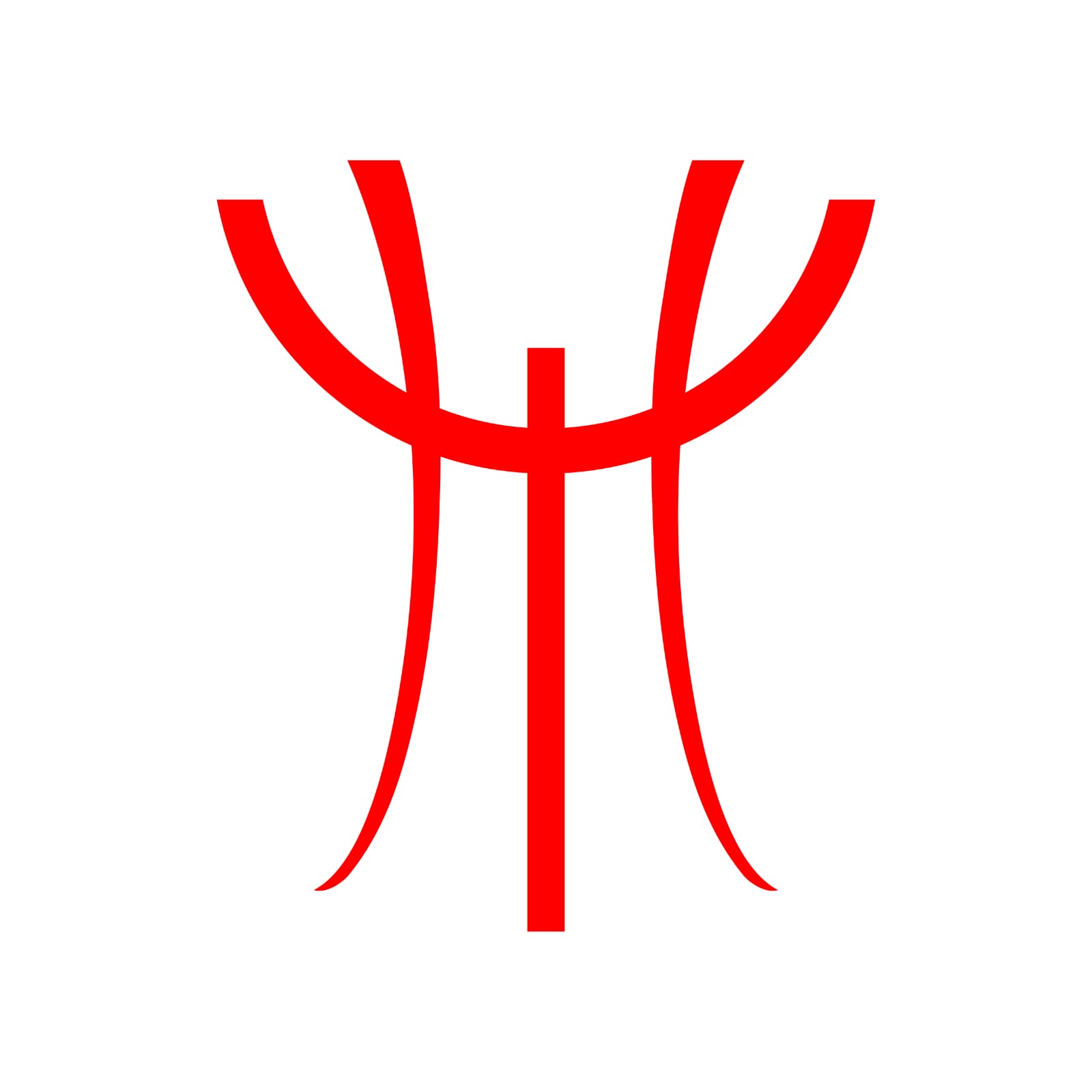
Tinggalkan Balasan