
PAPA NIA, 52 tahun, tengah mempersiapkan barang dagangannya. Sesekali ia berdiri mengusap keringat. Lalu kembali menunduk membersihkan meja plastik dan memasang karpet untuk alas tempat duduk para pembeli.
Pukul 3 sore itu dia mempersilakan saya di dekatnya menuju tempat yang sudah dia bersihkan. “Maaf, tempatnya belum rapi,” dia berkata. “Di sini tempatnya bagus, ba’angin (berangin), di samping komiu (kamu) bisa liat pemandangan gunung.”
Meski berasal dari Makassar, tapi dialeknya sudah bercampur dengan bahasa tutur orang Palu. “Saya memang sudah lama di Palu. Banyak orang sering mengira kalau saya orang Kaili.” Kaili adalah salah satu suku asli di Palu.
Pada 1986, Papa Nia mengikuti bapaknya berlayar ke Palu, yang berdagang pakaian. Awalnya jualan mereka cukup laris, tapi setelah lima tahun perlahan bangkrut, dan membuat bapaknya kembali ke Makassar. Tetapi, Papa Nia tetap memilih di Palu. Dia lantas bekerja di salah satu toko jual-beli mobil.
Setahun setelah bapaknya pulang, Papa Nia menikah dengan Mirna, anak dari teman dekat bapaknya yang juga dari Sulawesi Selatan. Mereka memiliki dua anak, laki dan perempuan. Keduanya telah bekerja di Jakarta. Anak perempuan bekerja sebagai wartawan; sementara yang laki-laki bekerja di sebuah bank negara.
“Anak saya yang pertama sudah empat tahun di Jakarta,” ujar Papa Nia sambil mengatakan tempat kerja anaknya. “Kalau anak kedua saya sudah lima tahun.”
Papa Nia adalah salah satu dari 88 pedagang kafe kecil di bagian timur Teluk Palu. Atas ajakan teman istrinya yang juga berjualan di sana, ia membangun usaha kafe sejak Juni 2013.
Kafe dia menjual menu seperti stik pisang, pisang goreng, mie ceplok, kopi, saraba, teh hangat dan lain sebagainya. Nyaris setiap hari, kafe itu dikunjungi para pelanggan, terutama anak-anak muda. Pemandangan pantai Talise menjadi daya tarik. Menurutnya, teluk di Talise merupakan teluk yang indah. Tidak semua daerah memiliki teluk seperti ini, terutama karena berada di kota. Paling penting, tempat ini menjadi tempat mencari nafka bagi puluhan orang di Kota Palu.
Sejak proyek reklamasi pantai Talise berjalan, Papa Nia menjadi khawatir bila sewaktu-waktu tempatnya ikut tergusur.
“Tempat ini punya pemerintah, kami hanya menyewa. Setiap bulan, kami menyetor uang taktis sebesar Rp50 ribu. Kami kasih ke Pak RW (Rukun Warga). Katanya dia yang berjuang untuk kami bisa berjualan di sini.”
“Saya bingung kalau tempat ini direklamasi. Kami mau cari nafkah dimana lagi? Sebagian tempat ini sudah ditimbun. Sekarang tidak lanjut, katanya izinnya bermasalah.”
Menurut Papa Nia, penimbunan pantai Talise sudah lama ditolak oleh mereka yang mengais nafkah di sekitar teluk seperti dirinya. Selain itu, ada juga nelayan dan petambak garam.
Menurut Papa Nia, “lemahnya persatuan masyarakat” menjadi salah satu faktor lemahnya suara penolakan terhadap reklamasi Teluk Palu. Bahkan ada juga yang mengancam. “Saya tahu beberapa orang yang menjadi tameng pemerintah,” klaimnya. “Mereka sudah dikasih uang. Makanya mereka rela mengorbankan kami yang hidup mencari nafkah di sini.”
Daeng Roja, 50 tahun, yang memiliki usaha kafe seperti Papa Nia, pernah mendapat ancaman karena memberikan pernyataan kepada salah satu media lokal Palu. Dia didatangi sekelompok orang tak dikenal.
“Jumlah mereka banyak, ratusan orang. Mereka mengobrak-abrik kursi dan meja. Bahkan salah satu dari mereka membuang meja dan kursi kelaut. Karena ada wartawan datang wawancarai saya. Saya bilang kalau kami menolak.Tidak ingin ada reklamasi di sini.”
“Mereka berteriak-teriak, ‘Kamu orang ini pendatang, jangan macam-macam di sini. Ini kampung kami, kalau tidak suka tempat ini direklamasi, keluar kalian dari sini.’”
Seperti halnya Papa Nia, seorang pedagang jagung yang berjualan dekat Patung Kuda juga berasal dari Makassar. Ia datang ke Kota Palu sejak 1967. Ia menjalani masa mudanya di kota ini dengan bekerja sebagai buruh bangunan, dari ikut mengerjakan rumah sakit daerah Palu, jembatan empat yang melintangi Pantai Talise.
“Dulu saya ikut babangun hotel itu, dan waktu itu baru hotel ini yang paling bagus di kota palu,” katanya sambil menunjuk Hotel Palu Golden, tak jauh dari tempatnya berjualan.
Pengehantian Sementara Reklamasi
Meski mendapat penolakan, reklamasi Teluk Palu tetap berjalan. Aktivitas penimbunan telah dilakukan sejak 2014. Area reklamasi masuk dalam dua lokasi dan dikerjakan oleh dua perusahaan swasta: lokasi reklamasi di Kelurahan Talise oleh PT Yauri Properti Investama seluas 38,33 ha, dan Kelurahan Lere oleh PT Mahakarya Putra Palu seluas 24,5ha.
Disebutkan, bahan galian untuk menimbun teluk diambill lewat izin pertambangan galian C, yang sudah direncanakan pemerintahan kota di enam kelurahan. Aktivitas keruk ini juga diprotes oleh masyarakat setempat (AJI Palu, 5/10/2015). Pada 21 Maret 2016, Forum Masyarakat Palu menutup dua titik lokasi reklamasi Teluk Palu. Forum adalah koalisi warga dari lima kelurahan yang terkena dampak dari rencana reklamasi (Antara Sulteng, 21/3/2016).
Dengan sejumlah protes seiring kegiatan pengerukan dan penimbunan, pemerintahan provinsi akhirnya “menghentikan sementara” reklamasi pantai Teluk Palu. Surat keputusan ini secara resmi dirilis pada akhir Mei 2016. Salah satu alasannya, ada tumpang-tindih aturan. Misalnya aturan sebelumnya sepanjang pantai itu ditetapkan sebagai lokasi wisata. Reklamasi merupakan upaya pemerintah menjadikan kawasan itu sebagai pusat bisnis dan perdagangan (Mongabay, 17/2/2016).
Klaim perusahaan daerah Kota Palu, kawasan reklamasi itu akan dibangun pusat “wisata terbesar dan termegah seperti mall, hotel, ruko, apartemen, pusat permainan hingga kuliner” (AJI Palu). Langkah kebijakan macam ini mencontoh apa yang sudah dilakukan di provinsi lain di sekitar Sulawesi, seperti pemerintah kota Makassar yang mereklamasi Pantai Losari dan Kota Manado di Teluk Manado.
Petambak Garam
Werman, 67 tahun, sedang membersihkan kotoran di tambak miliknya pada sabtu sore bulan Juli 2016. Tambak miliknya di pesisir Pantai Talise seluas 3×7 m2, yang dibagi menjadi tujuh petak kecil. Petak-petak itu berfungsi sebagai penampung air laut, pemanas air, dan tempat pembuatan garam. Lahan tambak itu warisan dari mendiang ayahnya. Selain menggarap lahan warisan, ia juga mengolah dua petak lagi milik keluarganya. Mengolah ladang garam di tempat itu merupakan pekerjaan rutin baginya sejak ayahnya meninggal.
Werman tidak sendiri memproduksi garam di Pantai Talise. Ada sedikitnya 160 orang yang memiliki tambak di lahan seluas kurang lebih 18 ha. Mereka tergabung dalam 16 kelompok tani garam, dan masing-masing kelompok terdiri 10-15 anggota. Kelompok ini dibentuk untuk mengorganisir bantuan-bantuan dari dinas pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan. Biasanya bantuan yang mereka terima seperti biaya untuk pembuatan tanggul dan mesin pompa air. Di lahan tambak ini ada 32 mesin pompa air, sehingga setiap kelompok memiliki 2 mesin pompa.
Proses kerja produksi garam bagi Werman bukanlah pekerjaan sulit dan berat. Mula-mula dia harus memindahkan air laut melalui parit yang terhubung ke bibir Pantai Talise, dengan bantuan mesin pompa air. Usai petak penampungan penuh, air dialirkan sedikit demi sedikit ke petak pemanas. Dari sana dialirkan ke petak-petak pembuatan garam untuk menunggu proses pengkristalan terjadi. Proses terakhir itu membutuhkan terik matahari dan laju angin guna mempercepat penguapan air tawar yang bercampur air laut. Ini biasanya berlangsung lima sampai enam hari. Barulah kemudian garam-garam dikumpulkan ke pinggiran petak, lantas dikarungkan dan siap dijual.
Di musim panas yang panjang—biasa dikenal badai El Nino antara Desember sampai Februari, Werman dapat memanen garam hingga 25–28 karung setiap dua pekan. Artinya, dalam sepekan dia bisa mendapatkan 16 karung garam. Ini berbeda ketika musim curah hujan tinggi atau dikenal badai La Nina, seperti terjadi di bulan ini, yang praktik menghambat proses produksi garam. Bisanya, di waktu senggang sembari terus memantau lahan garam, para penambak bekerja serabutan. Werman, misalnya, bekerja sebagai kuli bangunan, dengan upah Rp75 ribu/ hari. Para petambak garam di musim begini rata-rata hanya bisa menarik garam tak lebih dari 10 karung.
Tak semua petambak garam memiliki lahannya sendiri seperti Werman. Proses konsentrasi kepemilikan tambak ke segelintir orang sudah berlangsung di Pantai Talise. Bahkan ada lahan tambak yang sudah dimiliki sebuah bank. Karena itu, tak semua penggarap bekerja di lahan miliknya. Sebagian dari mereka menyewa lahan tambak dari si pemilik dengan rentang waktu dan uang tertentu—dikenal ba pajak. Ada pula yang disebut ba gade, yakni pemilik menggadaikan lahannya kepada si penggarap.
Meski pekerjaan menambak garam terlihat berat—membutuhkan tenaga dan diterpa panas terik selama berhari-hari, tetapi pekerjaan ini merupakan sumber utama pendapatan keluarga mereka. Rencana reklamasi di pantai Teluk Palu bisa menghambat mata pencaharian mereka.
Menurut Werman, penggaraman merupakan satu-satunya lahan yang dimilikinya. Menjualnya merupakan langkah yang salah. Apalagi bila sampai membiarkan lahan tambak ini rusak akibat dampak pembangunan kota. Itulah alasan kuat Werman berani menolak rencana reklamasi.
Dampak reklamasi ini pada akses air laut yang semakin jauh. Dengan penimbunan sebagian pesisir di Teluk Palu, para petambak makin sulit mendapatkan air laut.
Dirman, seorang petambak lain, mengatakan bahwa kabarnya pemerintah akan membuatkan saluran panjang untuk mengaliri tambak. “Tapi masalahnya bukan cuma air laut,” katanya.“Kami juga butuh angin untuk mempercepat penguapan.”Bila rencana reklamasi teluk terus berjalan, dan di atasnya dibangun gedung-gedung tinggi seperti mal sebagaimana klaim pemerintah, maka bangunan tinggi itu menghalangi angin laut ke lahan-lahan tambak.
“Saya tidak tahu apa yang direncanakan oleh pemerintah. Padahal masih banyak lahan kosong yang bisa dibangun gedung, dorang (pemerintah) malah menimbun laut. Tentu saja kami tolak,” kata Dirman.
___
Reportase dikerjakan oleh Adriansa Manu, Marianto Sabintoe, dan Moh. Amirudin A.
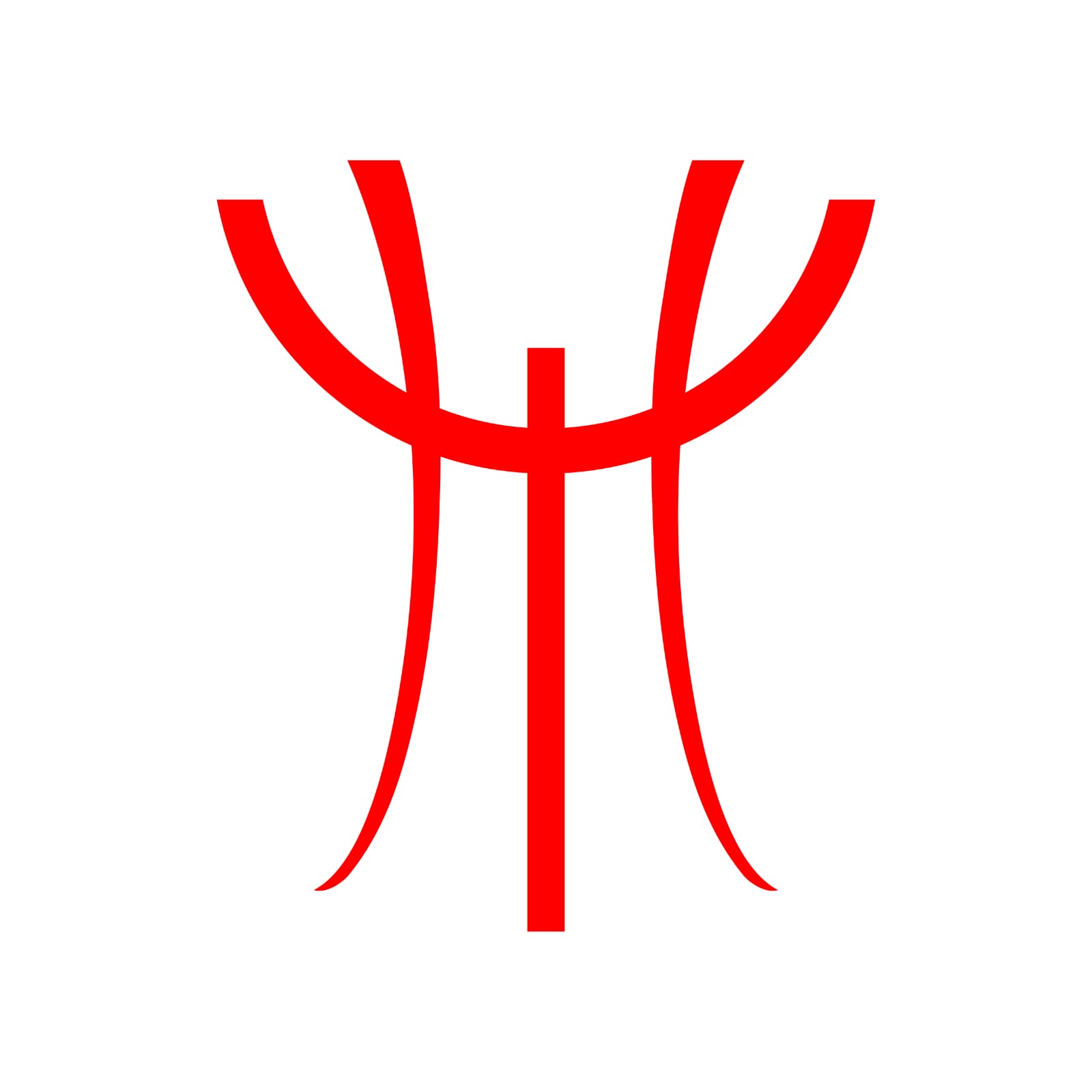
Tinggalkan Balasan