Oleh: Arianto Sangaji
Masyarakat adat punya karakteristik khusus sebagai kelompok penduduk pedesaan-pedalaman. Mereka hidup dalam suatu wilayah secara turun-temurun dan terus-menerus, dengan sistem kebudayaan dan aturan-aturan adat khas yang mengikat hubungan sosial di antara berbagai kelompok sosial di dalamnya.”
Noer Fauzi Rachman memberikan definisi tersebut dalam tulisannya, ”Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah-Airnya’” (Kompas, 11/6/2012). Definisi ini mewakili pandangan dominan yang melihat masyarakat adat semata dari segi identitas, dan sering kali romantik. Pandangan ini mengisolasi masyarakat adat dari aspek kegiatan produksi mereka yang jauh lebih kompleks.
Kategori ”penduduk pedesaan-pedalaman” sama sekali tak memberi informasi hubungan produksi macam apa yang hidup di masyarakat semacam itu. Kecuali segera muncul di kepala kita, kategori lain: mereka adalah petani. Karena masyarakat adat ada yang tinggal di pesisir pantai, maka bayangannya, mereka adalah nelayan, atau kombinasi di antara keduanya. Kita pun terjebak dengan homogenisasi: petani, nelayan, dan masyarakat adat sebagai kategori, tanpa isi.
”Pluralisme” kelas
Jalan keluarnya, masyarakat adat—yang terdiri dari petani dan nelayan—perlu dijelaskan dengan pendekatan kelas. Dengan memeriksa hubungan-hubungan produksi di antara mereka, kita bisa menemukan stratifikasi.
Misalnya, ada petani kaya, punya tanah luas, mempekerjakan petani-petani tidak bertanah sebagai buruh-upahan dengan hasil produksi untuk pasar. Ada petani dengan tanah seadanya untuk subsistensi keluarga, masuk hutan mengumpulkan hasil hutan untuk memperoleh uang tunai.
Ada juga petani miskin, yang tadinya punya tanah—karena macam-macam mekanisme— lantas secara perlahan tanahnya jatuh ke tengkulak atau petani kaya. Untuk menghidupi keluarga, mereka bekerja di lahan petani kaya dengan upah ditentukan sepihak atau bagi hasil yang tidak berimbang.
Jelas, para petani yang tinggal di ”pedesaan-pedalaman”, yang disebut masyarakat adat, karena proses sejarah tertentu melahirkan hubungan kelas di antara mereka.
Hubungan ini bersinggungan dengan relasi sosial lain, misalnya dominasi kekuasaan di antara mereka. Masyarakat dengan struktur kelas semacam ini tak bisa dengan sederhana diromantisasi sebagai masyarakat adat hanya karena ada faktor identitas tertentu yang mempersatukan mereka. Katakanlah kesamaan adat-istiadat, bahasa, dan simbol-simbol budaya yang lain.
Tentu tak ada masalah dengan segi identitas. Tapi, melupakan aspek struktur kelas internal, percakapan mengenai masyarakat adat berpotensi salah arah.
Kita boleh merayakan keanekaragaman dengan selalu menghormati dan menghargai perbedaan identitas, tetapi tidak boleh merayakan ”pluralisme” kelas. Sebab, itu berarti kita membiarkan kelas yang satu memakan bangkai kelas lain. Karena itu, gerakan masyarakat adat dalam skala lebih luas harus dibedakan dari usaha menghidupkan kesultanan, sebab yang terakhir ini identik dengan revitalisasi feodalisme: merayakan kelas.
Kuasa eksklusi
Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li (2011) di buku mereka, Powers of Exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia, menunjukkan empat faktor kuasa yang mengeksklusi pihak lain dari akses terhadap tanah di Asia Tenggara: (1) regulasi, terutama berhubungan dengan aneka peraturan sah dari negara; (2) pemaksaan dengan kekerasan, baik oleh negara maupun aktor non- negara; (3) pasar, yang membatasi akses ke tanah lewat mekanisme harga dan memberi insentif untuk klaim atas tanah yang lebih individualis; (4) legitimasi, yakni aneka bentuk justifikasi moral, seperti klaim hak turun-temurun, pertimbangan ilmiah, rasionalitas ekonomi, dan klaim pemerintah untuk mengatur.
Keempat aspek kuasa itu tepat menggambarkan kenyataan masyarakat adat disingkirkan dari tanah mereka, terutama melalui negara dan korporasi berbasis pengerukan sumber daya alam. Internasionalisasi pembuatan kebijakan strategis berkenaan dengan liberalisasi tanah melalui institusi-institusi supranasional (Bank Dunia, APEC, G-20, dan lain-lain) kemudian mengerangkeng pemerintah untuk menerjemahkannya menjadi kebijakan teknis adalah contoh konkret begitu dahsyatnya kuasa pasar. Kekerasan bersenjata atau ancaman kekerasan terhadap komunitas masyarakat adat yang menolak tanahnya dirampas tampak sudah biasa.
Sumber legitimasi dari keseluruhan proses itu adalah rasionalitas ekonomi: pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekspor, dan sebagainya. Praktik eksklusi semacam ini merupakan manifestasi langsung dari imperialisme di zaman sekarang.
Guna menentang proses eksklusi, moto masyarakat adat: ”Kalau negara tak mengakui kami, kami pun tak akan mengakui negara”, perlu diungkapkan secara lebih spesifik, yakni menolak negara kapitalis yang mempertuhankan pasar di atas segala-galanya.
Berbarengan dengan itu, kembali melihat internal komunitas adat, di mana kuasa eksklusi juga berpotensi bekerja dalam skala paling lokal. Eksklusi berbasis kelas ini juga mesti diakhiri.
Arianto Sangaji Kandidat PhD di Department of Geography, York University, Toronto
Sumber: cetak.kompas.com
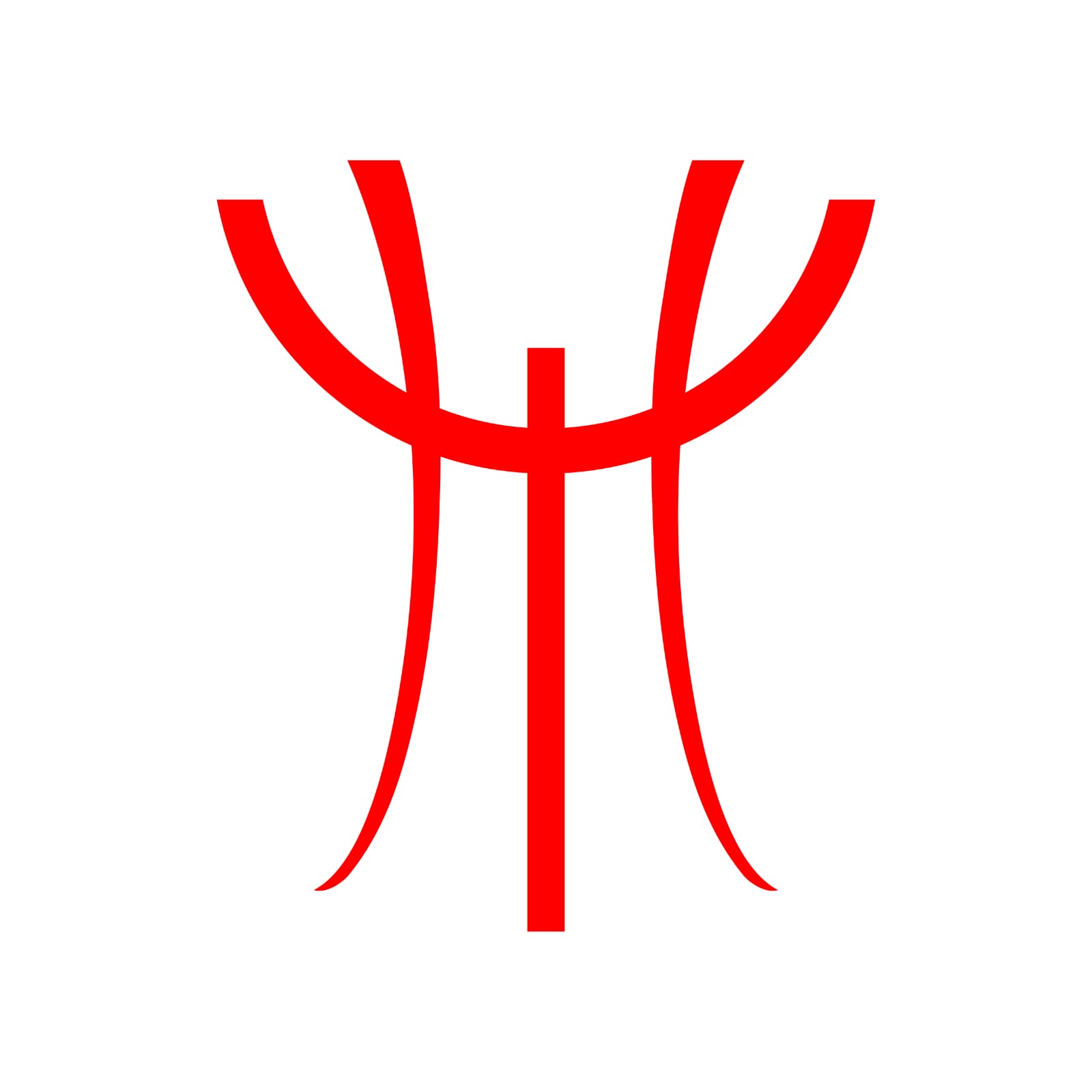

Tinggalkan Balasan