KERUSUHAN POSO DAN MOROWALI,
AKAR PERMASALAHAN DAN JALAN KELUARNYA
————————————————————————
Oleh George Junus Aditjondro
PENGANTAR:
AKHIR Oktober lalu, kaum terpelajar asal Poso dan Morowali yang berdiam di Sulawesi Tengah dan Jawa, khususnya yang menjadi anggota Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), dikejutkan oleh surat pimpinan gereja mereka ke Komisi I DPR-RI. Melalui surat bernomor MS GKST No. 79/X/2003, tertanggal 28 Oktober 2003, Pjs. MS GKST, pimpinan gereja terbesar di Sulawesi Tengah itu mengusulkan penetapan darurat sipil di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali. Surat itu ditandatangani oleh Ketua I Majelis Sinode GKST, Pendeta Arnold R. Tobondo dan Sekretaris I Majelis Sinode, Lies Sigilipu-Saino.
Sepintas lalu, surat itu menjawab kerinduan masyarakat Poso khususnya, yang pada tanggal 28 Desember lalu genap memperingati lima tahun pecahnya kerusuhan sosial yang telah menelan korban sedikitnya empat ribu nyawa. Apalagi selama tahun 2003 saja, insiden-insiden kekerasan tidak berkurang, bahkan sampai tanggal 27 Desember lalu, menurut catatan Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Poka RKP) mencapai 69 insiden, di mana ancaman dan ledakan bom menempati posisi teratas (35 insiden), disusul oleh penembakan dan pembunuhan oleh pelaku-pelaku yang tidak teridentifikasi (Radar Sulteng, 29 Desember 2003).
Tapi di fihak lain, surat pimpinan gereja terbesar di Sulawesi Tengah itu segera membawa ingatan kaum terpelajar asal Poso dan Morowali akan keadaan di Maluku, di mana status darurat sipil telah dijadikan justifikasi untuk penambahan penempatan pasukan TNI dan Polri di wilayah seribu pulau itu. Apalagi karena darurat sipil hanyalah selangkah menuju darurat militer, seperti di Aceh, di mana militer praktis berkuasa mutlak, dan kedudukan gubernur berada di bawah kedudukan panglima militer di sana. Praktis hanya itulah beda darurat militer dengan darurat sipil, di mana kedudukan penguasa darurat sipil berada di tangan Gubernur, yang umumnya kini dipegang oleh pejabat sipil.
Selain itu, status darurat sipil, kalau itu diberlakukan di daerah Poso dan Morowali, dapat membawa sesat berfikir dalam penanggulangan kerusuhan di sana. Pemberian status darurat sipil seolah-olah merupakan pembenaran bahwa kedua komunitas agama yang terbesar di Poso dan Morowali, yakni Nasrani dan Muslim, tidak lagi dapat memecahkan sengketa di antara warga-warga mereka dan hidup berdampingan secara damai. Padahal, baik akar kerusuhan di Poso dan Morowali, maupun faktor penyebab di balik berlanjutnya gangguan keamanan di kedua daerah itu, lebih banyak berada di luar masyarakat itu sendiri, sebagaimana yang akan diuraikan dalam makalah ini.
Supaya jelas gambaran perkembangan kerusuhan di Poso dan Morowali, saya akan lebih dulu membeberkan periodisasi konflik di daerah itu. Selanjutnya saya akan menguraikan akar-akar permasalahan yang mencetuskan dan melanggengkan konflik di sana, serta fihak-fihak yang sampai sekarang mendapatkan keuntungan dari pelestarian konflik itu, sebelum mengajukan saran-saran jalan keluar dari kemelut ini.
PERIODISASI KONFLIK DI DAERAH POSO-MOROWALI:
Gangguan keamanan di wilayah yang di akhir 1998 masih termasuk satu kabupaten (Poso) ini, sesungguhnya harus dibagi dalam tiga periode, yang ditandai oleh jenis gangguan keamanan yang tidak seluruhnya sama. Periode pertama, antara pecahnya kerusuhan di kota Poso tanggal 28 Desember 1998 s/d ‘gencatan senjata’ melalui pertemuan di Malino, Sulawesi Selatan, tanggal 20 Desember 2001. Periode kedua adalah periode pasca Pertemuan Malino s/d gelombang penyerangan terhadap Desa Beteleme di Kabupaten Morowali dan tiga desa di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso antara tanggal 10 dan 12 Oktober 2003. Sedangkan periode ketiga, pasca penyerangan terhadap Desa Beteleme sampai saat makalah ini ditulis.
Periode I: 25-28 Desember 1998 s/d Pertemuan Malino, 20- 21 Desember 2001:
Konflik antar komunitas ini sering diberi label sederhana, yakni “konflik agama”, dengan mengacu pada satu karakteristik dari komunitas-komunitas yang bertikai. Memang, pada awalnya konflik ini tercetus oleh perkelahian di antara dua orang pemuda yang berbeda agama, kemudian berkembang menjadi perkelahian di antara komunitas kampung-kampung Muslim dan Kristen, di mana selama gelombang kerusuhan pertama (Desember 1998) dan kedua (April 1998), terutama kelurahan-kelurahan Kristen di kota Poso menjadi sasaran penjarahan dan pembakaran, dibarengi dengan gelombang pengungsian penduduk Kristen dari kota Poso ke kota-kota Tentena (di Kabupaten Poso sebelah selatan), Palu, dan Bitung serta Manado (Sulawesi Utara).
Dalam saling menyerang antara komunitas Kristen dan Muslim di kota Poso itu, masing-masing fihak didukung oleh massa seiman dari luar kota Poso. Komunitas Muslim dibantu oleh orang-orang Tojo dari daerah Ampana (sebelah timur kota Poso; sekarang jadi ibukota Kabupaten Tojo Una-una) dan Parigi (Kabupaten Parigi Moutong, sebelah barat kabupaten Poso). Sementara komunitas Kristen dibantu oleh orang-orang Lage dari Desa-Desa Sepe dan Silanca di Kecamatan Lage (sebelah tenggara kota Poso).
Selanjutnya, sejak bulan Mei 2000 mulai berlangsung serangan-serangan balasan dari milisi Kristen yang terbentuk dari kalangan pengungsi Kristen di Tentena, yang terutama dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berasal dari kelompok Ondae di Kecamatan Pamona Timur. Kelompok sub-etnis Pamona ini adalah yang paling akhir memeluk agama Kristen, dan masih punya budaya perang – dan mengayau – yang baru satu generasi tertekan ke bawah permukaan.
Serangan balasan milisi pimpinan tokoh-tokoh masyarakat Ondae ini dibantu oleh relawan dari Lembah Napu (Kecamatan Lore Utara), yang tersinggung oleh pelanggaran adat yang dilakukan oleh orang-orang Parigi yang melintasi wilayah kekuasaan orang Napu di Poso Pesisir ketika membantu serangan komunitas Muslim di kota Poso. Selain itu, ada juga dukun-dukun dari suku Da’a (Kabupaten Donggala, Sulteng) dan Toraja (Sulsel) yang ikut membantu milisi Ondae dan Napu, termotivasi oleh semangat ‘membantu saudara seiman’, sama seperti motivasi orang Tojo dan Parigi membantu komunitas Muslim di kota Poso.
Ternyata, serangan balasan milisi-milisi suku-suku asli yang dominan Kristen ke kota Poso, kecamatan Lage dan kecamatan Poso Pesisir, yang semula dimaksudkan hanya untuk menangkap para provokator kerusuhan Poso gelombang I dan II, berkembang menjadi penghancuran kampung-kampung yang mayoritas berpenduduk Muslim di Kecamatan Lage dan Poso Pesisir. Ini terjadi setelah gugurnya Ir. Adven Lateka, pejabat asal Ondae yang memimpin serangan pertama yang gagal menangkap dan menculik para provokator, dan setelah kelompok-kelompok milisi penduduk asli yang mulai bermunculan secara spontan mendapat pengarahan dari seorang pensiunan militer asal Toraja, Tungkanan.
Dampak serangan balasan yang paling sering disorot adalah hancurnya kompleks pesantren di Km 9, selatan kota Poso, yang terkenal dengan sebutan Pesantren Walisongo. Peristiwa inilah kemudian di-blow up oleh sejumlah media Islam bergaris keras untuk menjustifikasi deployment lasykar-lasykar mujahidin dari Jawa, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, bahkan Sumatera Utara, membantu lasykar mujahidin lokal pimpinan Ustadz Adnan Arsal, seorang pegawai Departemen Agama Kabupaten Poso asal Sulawesi Selatan.
Kebebasan bergerak berbagai kelompok mujahidin dari luar – termasuk yang kemudian diidentifikasi sebagai Jamaah Islamiah — dijamin sepenuhnya oleh sejumlah pejabat pemerintah di Palu (provinsi) dan Poso (kabupaten). Sebelumnya telah beredar petunjuk-petunjuk perakitan senjata api di antara kedua komunitas agama di sana, yang serta merta menumbuhkan industri perakitan senjata di kedua komunitas. Hal ini dibarengi penyebaran amunisi ke kedua komunitas yang berasal dari sumber utama senjata dan amunisi Angkatan Darat, yakni PT Pindad. Namun dukungan yang lebih terbuka, yang sesungguhnya sudah dirintis oleh sejumlah perwira polisi dan tentara sejak pertengahan 2000, lebih banyak dinikmati oleh milisi Muslim, yang walaupun sangat majemuk dan penuh persaingan satu sama lain, seringkali hanya diberi satu label, yakni Lasykar Jihad.
Maka sempurnalah eskalasi konflik di antara kedua komunitas menjadi konflik bersenjata api, di mana komunitas Muslim berada di atas angin. Ini terbukti dari kehebatan serangan kilat ke lima desa di Kecamatan Poso Pesisir tanggal 27 s/d 29 November 2001, di mana serangan milisi Muslim mendapat dukungan sejumlah kendaraan dan alat-alat berat milik dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Poso. Peristriwa ini yang kemudian mengundang tekanan internasional, yang akhirnya mendorong Menko Kesra Yusuf Kalla memprakarsai pertemuan di kota dingin, Malino, 19-20 Desember 2001.
Memang, pertemuan di kota dingin itu berhasil memaksakan semacam “gencatan senjata” di antara kedua komunitas yang bertikai. Namun pertemuan itu juga melanggengkan ‘sesat fikir’ dalam melihat akar permasalahan konflik itu. Sebab yang ditekankan dalam pertemuan itu, serta berbagai pertemuan pendahuluannya yang juga dimediasi oleh Jusuf Kalla dan pejabat-pejabat lainnya, hanyalah agama dari para aktor. Bukan faktor-faktor lain, seperti etnisitas dan kelas.
Padahal, akar konflik itu, seperti yang akan saya uraikan di bagian-bagian berikut, adalah upaya komunitas-komunitas pribumi Poso – khususnya suku-suku Lore, Pamona, dan Mori – untuk memperjuangkan kedaulatan mereka di kampung halaman mereka sendiri. Kedaulatan yang mereka rasa sudah terancam oleh dominasi para migran dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Terutama setelah pembangunan jalan raya Trans-Sulawesi mempermudah arus migrasi dari Selatan ke Kabupaten Poso yang kaya dengan berbagai sumber daya alam.
Perlawanan komunitas-komunitas pribumi Poso sejak kerusuhan gelombang ketiga, juga lebih bercorak etnis ketimbang Kristen. Baik ritus-ritus yang dijalankan untuk menyiapkan penyerangan – seperti ritus dimandikan oleh orang-orang tua yang dipandang punya kekuatan magis, untuk mendapatkan kekebalan — sampai dengan pantangan menyembelih hewan piaraan di kampung, selama milisi pergi menyerang, bukan digali dari tradisi Kristen, tapi lebih banyak dari tradisi-tradisi Pamona pra-Kristen. Memang, ada kepercayaan yang dipegang teguh oleh milisi-milisi penduduk asli yang sejalan dengan ajaran Kristen, misalnya larangan memaki, mencuri, serta memperkosa perempuan komunitas lawan yang diserang.
Tapi jangan keliru, larangan-larangan itu dipegang teguh bukan untuk memperoleh keselamatan di sorga, melainkan untuk memperoleh kemenangan dalam perang. Makanya, Wens Tinagari, satu-satunya anggota milisi yang diketahui melakukan pemerkosaan dalam penyerangan ke kompleks pesantren Walisongo, dieksekusi oleh kawan-kawannya sendiri. Hukuman, yang tentu saja bertentangan dengan ajaran Kristen. Sementara semboyan yang ditanamkan di antara para anggota milisi adalah bahwa mereka berperang untuk merebut kembali tanah adat mereka dari para pendatang yang telah mencemarkan tanah adat mereka. Kelakuan para pendatang dianggap mengingkari Maklumat Raja Talasa Tua, raja Poso yang terakhir, ketika membagi-bagi Poso kepada para pendatang dari luar pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 1947.
Makanya, paradigma ‘konflik agama’ sudah harus diganti dengan paradigma ketergusuran komunitas-komunitas pribumi Kabupaten Poso. Makalah ini lebih menyoroti komunitas-komunitas pribumi yang beragama Kristen, sebab merekalah yang kini paling tergusur dari pusat-pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya.
Periode II: pasca Deklarasi Malino s/d penyerangan terhadap empat desa Kristen di Morowali dan Poso:
Sementara sepuluh butir kesepakatan Deklarasi Malino mulai disosialisasikan, gangguan keamanan di Kabupaten Poso dan Morowali, yang telah dimekarkan dari kabupaten induknya, mulai berubah bentuk. Baku serang di antara kedua komunitas praktis sudah tidak terjadi, dan gangguan keamanan berubah bentuk menjadi teror dari ‘kelompok-kelompok yang tidak teridentifikasi’ terhadap rakyat di kedua kabupaten itu. Dari silih bergantinya sasaran teror tersebut, tampaknya teror itu bertujuan untuk memprovokasi konflik antar komunitas kembali. Namun kenyataannya, kedua komunitas tidak terprovokasi.
Ada tiga bentuk teror yang dialami penduduk di kedua kabupaten itu. Bentuk teror pertama yang paling sering terjadi adalah ancaman dan ledakan bom. Bentuk teror yang kedua yang sedikit lebih rendah frekuensinya adalah penembakan oleh penembak profesional yang tidak teridentifikasi jati dirinya (‘penembak misterius’). Sedangkan bentuk teror yang ketiga, yang lebih jarang terjadi adalah serangan kilat oleh perusuh terlatih bersenjata otomatis di saat fajar atau tengah malam, pada saat penduduk sedang terlelap.
Periode III: Medio Oktober 2003 sampai sekarang:
Spiral kekerasan tercetus kembali dengan serangan ‘pasukan terlatih bersenjata’ – meminjam istilah rekan saya, Arianto Sangaji – ke Desa Beteleme di Kabupaten Morowali, tanggal 10 Oktober 2003, yang disusul dengan serangan ke tiga desa di Kecamatan Poso Pesisir, dua hari berikutnya.
Operasi keamanan gabungan TNI dan Polri yang segera dilansir setelah penyerangan beruntun di Morowali dan Poso itu mendapat sorotan media nasional dan internasional, mengungkapkan bahwa para aktor di lapangan kebanyakan adalah aktivis-aktivis Muslim yang berasal dari daerah Poso, Ampana, dan Morowali sendiri. Celakanya, penyidikan lebih jauh tentang siapa yang mengorganisir mereka, menemukan jalan buntu dengan terbunuhnya tokoh yang dianggap pemimpin penyerangan ke Beteleme, yakni Muhamadong alias Madong.
Akibat kecerobohan aparat keamanan gabungan itu, bukan hanya Madong yang tertembak mati, melainkan juga sejumlah aktivis Muslim lain yang berasal dari Poso, Ampana dan Poso Pesisir. Kecerobohan itu dampaknya bagaikan menyiram bensin ke api. Bagaikan mengelu-elukan para pejuang intifada di Palestina, penguburan aktivis-aktivis Muslim yang ditembak mati oleh aparat menjadi ajang mobiliasi semangat jihad baru, tidak hanya jihad melawan komunitas Kristen tapi juga jihad terhadap aparat Polri. Memang, pada saat arak-arakan keliling kota Poso mengantar jenazah Aswan, salah seorang di antara enam tersangka penyerang Desa Beteleme, beredar selebaran berisi lima butir imbauan berjihad. Begitu pula, setelah Hamid tertembak oleh Brimob di Poso Pesisir, jenazahnya juga diarak oleh massa Muslim sebelum dikuburkan di pekuburan Muslim di Kelurahan Lawanga di kota Poso (Kedaulatan Rakyat, 17 Nov. 2003; Manado Post, 17 Nov. 2003; Komentar, 17 & 22 Nov. 2003).
Dalam suasana panas beginilah, Bendahara Majelis Sinode GKST, Oranye Tadjodja (58), dibunuh setelah disiksa di bangunan bekas Hotel Kartika di tepi Jalan Raya Trans Sulawesi di Kelurahan Kayamanya pada hari Sabtu siang, 15 November 2003. Ketua DPC Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Poso itu dibunuh bersama Yohannes (“Butje”) Tadjodja, keponakan yang juga jadi sopirnya waktu itu, yang lehernya hampir putus ditebas. Nampaknya untuk mengalihkan jejak, kelompok pembunuhnya melarikan mobil Toyota Kijang DN 440 E milik almarhum bersama jenazah kedua korban ke Kecamatan Poso Pesisir dan meninggalkannya di lembah Sungai Puna. Dengan demikian, bisa timbul kesan bahwa tokoh Kristen itu dibunuh oleh massa Muslim di Poso Pesisir yang sedang marah akibat ditembaknya seorang warga mereka, Hamid alias Ami, oleh satuan Brimob yang datang menangkap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam penyerangan di Poso Pesisir tanggal 12 Oktober 2003 (RKP News, 16 Nov. 2003; Suara Pembaruan, Bernas & Manado Post, 17 Nov. 2003; sumber-sumber lain).
Dugaan itu masuk akal, lantaran semangat baku balas dendam sedang menggelora kembali. Ribuan warga Muslim yang berdemonstrasi di depan Markas Polres Poso pada hari Minggu, 16 November, memprotes penembakan Hamid dan menuntut pembebasan dua orang kawannya, Irwan bin Rais dan Sukri. Mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada Deny Lingkuwa (22), seorang warga Desa Wawopada, Kabupaten Morowali yang baru saja lulus dari testing calon pegawai negeri sipil di Departemen Agama Poso. Pemuda malang berambut cepak itu tewas dianiaya massa yang keliru menyangka dia intel polisi. Motor Yamaha Shogun yang korban kendarai hangus dibakar massa. Begitu pula sebuah motor sumbangan Menko Kesra Jusuf Kalla yang diparkir di depan Markas Kompi IV Pelopor Brimob Polda Sulteng di Kelurahan Mo-engko di pinggiran barat kota Poso (RKP News, 16 Nov. 2003; Radar Sulteng, 16 Nov. 2003; Suara Pembaruan, Kedaulatan Rakyat, Komentar & Manado Post, 17 Nov. 2003; sumber-sumber lain).
Sementara itu, dua bentuk teror, yakni bom dan penembakan misterius, terus terjadi. Sebuah bom juga meletus di daerah Lembomawo ketika umat Kristen di sana sedang menyiapkan diri untuk merayakan Natal, 25 Desember lalu. Untunglah tidak sampai ada korban. Tapi yang lebih menguntungkan lagi adalah bahwa gangguan-gangguan keamanan itu tidak sampai membakar kembali semangat baku serang di antara kedua komunitas agama, yang sesungguhnya mewakili masyarakat asli dan masyarakat pendatang, atau mewakili yang tersisih dan yang menjadi kelompok dominan di bidang politik, ekonomi dan budaya.
AKAR PERMASALAHAN:
(a). Faktor-faktor lokal:
a.1. Marjinalisasi terbalik:
Proses marjinalisasi terbalik antara penduduk kota Poso dan penduduk pedalaman Kabupaten Poso, yang memperlebar jurang sosial antara penduduk asli dan pendatang. Maksud saya, di pedalaman Poso tiga suku penduduk asli yang mayoritas beragama Kristen – yakni Lore, Pamona, dan Mori – mengalami marjinalisasi di bidang ekonomi, politik, dan budaya, sehingga dibandingkan dengan para pendatang, mereka ini merasa tidak lagi menjadi tuan di tanahnya sendiri. Tapi sebaliknya, di kota Poso – di lokasi di mana kerusuhan meletus dan perusakan paling parah terjadi – adalah para turunan pendatang dari Gorontalolah yang paling mengalami marjinalisasi dibandingkan dengan penduduk asli yang bermukim di kota Poso, sebelum kerusuhan 1998-2000.
a.1.1. Marjinalisasi penduduk asli beragama Kristen di pedalaman Kabupaten Poso:
Mari saya jelaskan dulu proses marjinalisasi yang dialami oleh ketiga suku penduduk asli yang beragama Kristen di pedalaman Kabupaten Poso. Pertama-tama, marjinalisasi ekonomi mereka alami, sebagian juga karena strategi penginjilan oleh para misionaris Belanda, yang kemudian diteruskan oleh GKST, yang tidak menumbuhkan kelas menengah yang mampu berwiraswasta dan bersaing dengan para pendatang. Strategi pendidikan Zending dan kemudian GKST lebih mengfasilitasi transformasi profesi dari petani ke pegawai (ambtenaar), baik pegawai pemerintah maupun pegawai gereja. Ini sangat berbeda dengan strategi penginjilan di Tana Toraja dan Minahasa, di mana sudah muncul banyak pengusaha tangguh berkaliber nasional.
Agama baru yang disebarkan oleh para misionaris itu, seperti di banyak tempat di Nusantara, juga mengakibatkan desakralisasi alam dan pelunturan hak ulayat. Ini pada mulanya lebih berlaku di tanah-tanah yang ditanami tanaman perdagangan, seperti cengkeh, sementara di daerah yang ditanami padi berbagai upacara yang berakar di agama suku, misalnya padungku, pesta syukur sesudah panen, masih berlaku. Tapi lama kelamaan, hak ulayat sudah mulai meluntur juga di daerah pertanian padi.
Transformasi sosial-ekonomi yang mula-mula berjalan perlahan kemudian dipacu akibat pembangunan Jalan Raya Trans-Sulawesi, yang memicu arus migrasi besar-besaran dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah. Arus migran Bugis, Makassar, Mandar, Luwu, dan Toraja semakin memacu peralihan penguasaan tanah dari penduduk asli ke pendatang.
Permintaan tanah oleh pendatang kemudian bersinerji dengan penjualan tanah oleh penduduk asli untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, dan selesai dari pendidikan tertier, tanah dijual lagi untuk membiayai sogokan untuk menjadi pegawai negeri, yang di daerah Palopo dan Palu sudah naik dari Rp 15 juta s/d Rp 25 juta, untuk pos-pos yang tidak terlalu basah di bidang pendidikan. Bayangkan berapa lagi yang harus dibayar untuk menjadi pegawai dinas-dinas yang lebih basah, seperti PU, Dinas Pendapatan Daerah, Bank Pembangunan Daerah, dan lain-lain.
Sementara marjinalisasi ekonomi penduduk asli beragama Kristen berjalan, muncul juga marjinalisasi di bidang politik. Kemunculan tokoh-tokoh penduduk asli Kristen di bidang politik banyak terhambat oleh rivalitas di antara ketiga kelompok etno-linguistik itu (Pamona, Mori, dan Lore), dan tidak kalah hebatnya, di antara anak-anak suku Pamona sendiri.
Sementara itu, muncullah generasi muda beragama Islam yang juga sudah berpendidikan tertier, baik yang berasal dari masyarakat turunan Gorontalo dan Jawa di kota Poso, maupun dari suku-suku asli yang dominan Muslim, seperti Tojo dan Bungku. Mereka juga mulai menuntut lebih banyak posisi di bidang pemerintahan, dan untuk mencapai tujuan mereka, mulai lebih banyak berkiprah di berbagai partai, ormas, dan organisasi lain yang dapat memberikan paspor ke pusat kekuasaan, seperti ICMI, Golkar, dan untuk sementara waktu, Partai Daulat Rakyat (PDR), yang dibentuk oleh para pendukung Menteri Koperasi & UKM, Adi Sasono. Kompetisi yang semakin tajam ini tampaknya kurang diantisipasi oleh generasi muda terpelajar yang beragama Kristen.
Mereka sudah jatuh, ditimpa tangga. Setelah mengalami marjinalisasi di bidang ekonomi dan politik itu, penduduk asli yang mayoritas beragama Kristen mulai mengalami marjinalisasi di bidang budaya, terutama di tahun-tahun menjelang pecahnya konflik Poso. Ada beberapa faktor yang mendorong marjinalisasi itu, seperti sejumlah larangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni larangan bagi orang Islam berjabat salam antara orang-orang yang berbeda jenis kelamin dan bukan suami isteri; larangan bagi orang Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada kerabat dan kenalan mereka yang beragama Kristen; dan larangan menyelenggarakan acara-acara Natalan bersama di kantor-kantor pemerintah.
Faktor-faktor lain adalah semakin dominannya peranan ICMI dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri, dominasi Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang puritan dan kurang simpatik terhadap budaya-budaya setempat; serta dominasi para pendatang dari Sulawesi Selatan sampai ke tingkat imam mesjid dan melalui para dai utusan Pesantren Hidayatullah, Kaltim, sampai ke desa-desa, khususnya di Kecamatan Tojo dan Poso Pesisir.
Marjinalisasi kultural terhadap penduduk asli yang beragama Kristen semakin memuncak setelah para mujahidin dari berbagai lasykar menguasai roda pemerintahan di kota Poso. Lasykar-lasykar penganut aliran Wahabi dari Arab Saudi memaksa semua perempuan mengenakan jilbab di luar rumah. Mereka juga melarang modero, tari pergaulan Poso, di tempat-tempat publik, melarang peredaran minuman beralkohol, termasuk saguer (nira pohon aren), sampai-sampai melarang penggunaan logat Poso yang dipengaruhi logat Manado di tempat-tempat umum.
a.1.2. Marjinalisasi dan radikalisasi migran Muslim di kota Poso:
Sebelum menggambarkan proses marjinalisasi dan sekaligus radikalisasi masyarakat migran Muslim di kota Poso, kita perlu lebih dulu mengenal keragaman etnik penduduk kota Poso, serta pelapisan sosial yang ada sebelum kerusuhan 1998. Keragaman etnik penduduk kota Poso, merupakan suatu keadaan yang sejak awal ditolerir oleh Raja Talasa Tua (Nduwa Talasa ), penguasa adat terakhir kota Poso. Kata sang raja dalam maklumatnya yang dibacakan di kantor raja Poso di kota Poso, tanggal 11 Mei 1947, jam 10 pagi:
Laut/Teluk Tomini tidak ada pagarnya
Laut/Teluk Tomini tidak ada pagarnya
Hai kamu orang Arab
Hai kamu orang Tionghoa
Hai kamu orang Jawa
Hai kamu orang Manado
Hai kamu orang Gorontalo
Hai kamu orang Parigi
Hai kamu orang Kaili
Hai kamu orang Tojo
Hai kamu orang Ampana
Hai kamu orang Bungku
Hai kamu orang Bugis – orang Wotu
Hai kamu orang Makassar
Jika kamu tidak menaati perintahku kamu boleh pulang baik-baik ke kampung halamanmu karena Tana Poso tidak boleh dikotori dengan darah
(Damanik 2003: 41).
Sementara itu, dari sudut sosial-ekonomi, masyarakat kota Poso dapat dibagi dalam tiga kelas, yakni (a) kelas bawah lama; (b) kelas menengah lama; (c) kelas atas lama. Kelas bawah lama terutama terdiri dari keturunan para migran Gorontalo yang mayoritasnya bermukim di Kelurahan-Kelurahan Lawanga, Bonesompe, dan Kayamanya. Profesi mereka kebanyakan adalah nelayan dan buruh pelabuhan, yang mengalami marjinalisasi karena pergantian kekuasaan politik nasional tahun 1965-1966 dan agak lama kemudian, pembangunan Jalan Trans-Sulawesi. Kelas menengah lama terutama terdiri dari komunitas-komunitas asli Poso, Mori, dan Minahasa, yang kebanyakan terdiri dari para birokrat yang masih tetap juga berkebun di tanah-tanah mereka di seputar pemukiman mereka. Sedangkan kelas atas lama terdiri dari kaum usahawan berdarah Arab dan Tionghoa.
Sebelum munculnya rezim Orde Baru, buruh pelabuhan terhimpun dalam tiga organisasi. Pertama, Serikat Buruh Pengusahaan Pelabuhan (SBPP) yang bernaung di bawah SOBSI, yang pada gilirannya bernaung di bawah Partai Komunis Indonesia. Kedua, organisasi buruh yang bernaung di bawah PNI, dan ketiga, organisasi buruh yang bernaung di bawah Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).
Akibat Surat Perintah 11 Maret 1966, SBPP dibubarkan, dan para anggotanya dikenakan wajib lapor setiap hari Senin di kantor Kodim 1307 Poso. Selanjutnya, setelah gerakan organisasi-organisasi massa binaan Angkatan Darat melanjutkan agitasinya untuk menggulingkan pemerintah Soekarno yang berbasis di PNI, organisasi buruh berideologi nasionalis pun dibubarkan. Tinggallah organisasi buruh pelabuhan di bawah PSII, yang dipimpin oleh Yahya Mangun, seorang migran asal Gorontalo yang bermukim di Kelurahan Lawanga. Organisasi itu kemudian memegang hegemoni kekuasaan dalam pengorganisasian buruh di kota Poso, dan menjadi tulang punggung Muhammadiyah cabang Poso serta organisasi-organisasi Muslim militan yang muncul ke permukaan sesudah gelombang pertama kerusuhan Poso.
Antara bulan Maret-April 1966, meletuslah peristiwa pertama yang mengarah pada radikalisasi kelompok Muslim kota Poso, yang juga merupakan awal aliansi militer dengan kelompok Islam radikal di kota Poso. Komandan Kodim 1307 Poso waktu itu, Letkol Sutikno Slamet, berusaha menggulingkan Bupati Bartolomeus Lallung (B.L.) Sallata (1962-1967). Alasannya, Bupati yang berasal dari PNI itu merupakan unsur Orde Lama, bukan orang asli Poso (ia kelahiran Desa Batualla, Makale, Toraja), dan beragama Kristen. Untuk itu sang Dandim berkampanye melalui forum Panca Tunggal yang beranggotakan Dandim, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Bupati sendiri mendapat dukungan dari Kapolres Poso, AKBP Raden Bey.
Di luar forum Panca Tunggal, kampanye penggulingan Bupati Sallata mendapat dukungan dari Yahya Mangun, tokoh buruh PSII, dan seorang tokoh Muslim, Ali Adam, Direktur SGA Negeri Poso. Tetapi usaha penggulingan sang bupati secara legal susah, sebab DPRD-GR Kabupaten Poso waktu itu didominasi oleh PNI, dan diketuai oleh seorang politikus asal Pamona yang beragama Kristen, J. Santoyu. Makanya, karena sudah tidak sabar, Dandim mengerahkan pasukannya untuk mengepung kantor DPRD-GR Poso, untuk memaksa para wakil rakyat mencabut dukungan mereka pada Sallata. Sebelumnya, kantor dan rumah Bupati sudah dikepung juga oleh personil militer Kodim Poso.
Usaha kudeta itu gagal, karena anggota BPH Bidang Ekonomi yang juga seorang kader PNI, H. Usman Sondeng, berhasil lolos dari kepungan militer, dan melaporkan tindakan sang Dandim ke atasannya di Palu. Dalam waktu singkat, Sutikno Slamet serta Raden Bey dicopot dari posisi mereka masing-masing sebagai Dandim dan Kapolres, dan diperiksa oleh atasan mereka masing-masing. Sementara itu, para anggota Panca Tunggal diganti semua, kecuali sang Bupati, yang diberi kesempatan menyelesaikan masa jabatannya sampai tahun 1968 tanpa halangan. Begitu tutur Usman Sondeng yang kini anggota DPRD Sulawesi Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, kepada penulis di Palu, akhir Desember lalu.
Sesungguhnya, menurut Sondeng, motif utama usaha perebutan kekuasaan militer yang beraliansi dengan kelompok Muslim ekstrim di kota Poso adalah perebutan hegemoni perdagangan kopra. Waktu itu, Bupati Poso secara ex officio menjabat sebagai ketua Pusat Koperasi Kopra (PKK), yang berhak membagi-bagi jatah ekspor kopra kepada berbagai organisasi ekonomi dan politik di Kabupaten Poso. Sang Dandim tidak puas dengan jatah ekspor kopra yang diberikan kepada Kodim Poso, dan ingin mendapatkan jatah yang lebih besar. Maklumlah, kopra merupakan komoditi yang sangat menguntungkan waktu itu. Terbukti bahwa kegiatan pemerintahan Kabupaten Poso hampir sepenuhnya dibiayai dari hasil ekspor kopra.[1]
Sementara itu, proses marjinalisasi kelas bawah kota Poso terus berlangsung. Anak-anak buruh pelabuhan yang orangtuanya terlibat dalam ormas buruh yang berafiliasi ke SOBSI, jadi korban kebijakan ‘litsus’ (penelitian khusus bersih lingkungan) di masa kekuasaan Menko Polkam Admiral Sudomo. Walaupun mereka punya ijazah SLTA atau Sarjana, mereka tidak dapat melamar pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Banyak di antara mereka kemudian berpaling ke laut, menjadi nelayan.
Akhirnya, kelas bawah kota Poso itu sudah jatuh ditimpa tangga pula. Pembangunan Jalan Raya Trans-Sulawesi semakin mempersempit lapangan kerja mereka. Kalau dulu setiap hari ada kapal yang berlabuh dan membongkar muat barang dan penumpang di pelabuhan Poso, setelah jalan lintas Sulawesi itu terbangun, sekarang praktis hanya ada sebuah kapal yang bersandar di pelabuhan itu setiap bulan. Sementara itu, bandara Kasiguncu dekat kota Poso sudah lebih dulu mati, setelah penerbangan pesawat perintis Merpati dan MAF berhenti menghubungkan kota-kota Tentena dan Poso dengan Lembah-Lembah Pegunungan Tokolekaju dan kota Palu (lihat Aditjondro 2003: xxi-xxii).
Proses marjinalisasi kelas bawah itu, dibarengi dengan proses radikalisasi komunitas Muslim di kota Poso. Migrasi orang Gorontalo dari Utara dan orang-orang Bugis, Makassar, Luwu dan Mandar dari Selatan semakin memperkuat posisi Muhammadiyah di kota Poso. Salah satu kiprah organisasi massa Islam itu adalah pesantren Walisongo di Km 9 sebelah selatan kota Poso, yang didirikan oleh Ali Adam, tokoh Muslim Poso yang pernah berkolaborasi dengan Dandim Poso dalam kudeta gagal tahun 1966.
Pertumbuhan kelompok radikal Muslim di antara para migran asal Gorontalo dan Sulawesi Selatan agak tertekan ke bawah permukaan selama masa pemerintahan bupati-bupati Poso yang berlatarbelakang militer, yakni Kol. RPMH Koeswandi (1973-1984) dan Kol. Soegijono (1984-1988). Lebih-lebih di bawah Koeswandi, perwira TNI/AD asal Madura, yang beragama Kristen Protestan, dan aktif berusaha menumbuhkan semangat pluralisme di antara komunitas-komunitas agama di kota dan kabupaten Poso. Hal ini tidak disukai oleh tokoh-tokoh Muslim yang ingin memperjuangkan hegemoni politik Islam di kota dan kabupaten Poso.
Mereka baru mendapat angin di masa pemerintahan Bupati Arief Patanga, yang juga mengawali konflik antar agama dan suku di Poso. Sebelum memangku jabatan Bupati pun, Arief Patanga sudah terlibat dalam usaha mengadu domba kelompok-kelompok etnis di Kabupaten Poso lama. Tahun 1983, ia dikonsultasi oleh alm. Holy Abdul Karim, seorang pejabat asal Una-una (waktu itu masih termasuk Kabupaten Poso), yang menulis surat tentang kemampuan beberapa kelompok etno-linguistik (suku) di kabupaten itu untuk menjadi Bupati Poso.
Dalam surat setebal 3-4 halaman yang dimaksudkan sebagai masukan untuk Bupati Koeswandi dalam rangka suksesi jabatannya, disebutkan bahwa hanya orang Tojo yang dapat dipercayai memangku jabatan Bupati di Poso. Orang Pamona, menurut penulis surat itu, hanya punya kepedulian utama untuk membangun gereja, sementara orang Bungku terlalu malas. Munculnya surat yang kemudian dikenal sebagai “surat SARA” mengundang kemarahan tokoh-tokoh Pamona di kota Poso. Masalah itu akhirnya diselesaikan secara adat walaupun tidak sepenuhnya memenuhi kriteria (Tengko, t.t.; sumber-sumber lain).
Surat Holy Abdul Karim nyaris berbuntut perkelahian antara Holy dengan seorang mahasiswa suku Pamona, yang di kemudian hari memimpin serangan balasan orang Pamona ke kota Poso. Adven Lindo (A.L. Lateka), yang waktu itu masih menuntut ilmu di Makassar, datang menemui Holy di ruang kerjanya, a.l. karena namanya ikut disebut dalam surat itu. Lindo hampir saja memukul Holy, tapi masih dapat menahan diri dan hanya memukul meja kerja dan menendang kaki sang birokrat asal Una-una. Begitu tutur seorang narasumber, yang mengenal almarhum A.L.Lateka sejak 1964.
Akibat munculnya surat itu, suksesi Bupati Poso menampilkan seorang tentara lagi, yakni Kol. Soegijono (1984-1988), disusul oleh seorang pejabat bupati asal Toraja, J.W. Sarapang (1988-1989), sebelum Arief Patanga berhasil mengorbitkan diri menjadi Bupati, tahun 1990. Di saat itulah iklim politik nasional selama sewindu terakhir kepresidenan Soeharto sudah menjadi semakin sektarian, yang direspons dengan lihai oleh Patanga sebagai Ketua ICMI Kabupaten Poso. Di bawah ketiak Patanga, kelompok Muslim yang menolak pendekatan kultural yang lebih pluralis sangat mendapat angin. Secara finansial mereka mendapat keuntungan dari proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Poso yang dilimpahkan kepada mereka sebagai kroni bisnis keluarga Patanga.
Menjelang gelombang pertama kerusuhan di Poso mereka mengorganisir diri menjadi Forum Silaturahmi & Perjuangan Umat Islam (FSPUI) yang diketuai oleh Adnan Arsal, seorang pegawai Departemen Agama Kabupaten Poso, dengan Sekretaris, Hasan Lasiata. Cikal bakal organisasi itu adalah pertemuan rutin yang sering diadakan oleh Agfar Patanga, adik sang bupati, di rumah dinas bupati, bersama delapan orang tokoh Muslim garis keras di Poso. Karena jumlahnya sembilan, kelompok ini dikenal dengan sebutan “Wali Songo” (sembilan wali).
a.2. Melebarnya jurang kaya-miskin yang tumpang-tindih dengan komunitas agama dan etnis:
Sesungguhnya, komunitas asli Poso yang mayoritas Kristen juga punya andil dalam mempertajam hubungan antar komunitas di kota Poso. Sejumlah pejabat yang beragama Kristen, yang mulai direkrut oleh Bupati Koeswandi, merintis praktek korupsi dana-dana publik di kabupaten itu. Sebagai contoh dapat disebutkan peranan J. Santoyu, bekas Ketua DPRD Kabupaten Poso di zaman Bupati Salata, yang lama menjabat sebagai Kepala Dinas P&K di zaman Bupati Koeswandi. Atau J. Kogege, Ketua Bappeda Kabupaten Poso di bawah tiga orang Bupati, yakni Koeswandi, Soegiyono, dan Arief Patanga di masa jabatannya yang pertama (Aditjondro 2003: xxii-xxiii).
Di masa jabatan Koeswandi, hasil korupsi itu belum dipamerkan dalam bentuk rumah-rumah megah dan mewah di Kelurahan Lombogia, sebab Koeswandi sendiri dikenal sebagai bupati yang bersih. Tapi selesai masa jabatan Koeswandi, rumah-rumah dan mobil-mobil mewah – tentu saja, untuk ukuran kota Poso – mulai bermunculan di Lombogia, yang tentu saja menjadi duri pencocok mata penduduk Lawanga, kelurahan miskin tetangganya. Sedangkan Kogege lebih lihai menginvestasikan kekayaan hasil korupsinya dalam sebuah hotel, Alamanda, di jalan Pulau Bali di Kelurahan Gebangrejo.
a.3. Oposisi rakyat + PDI versus demo preman pro-rezim:
Di masa jabatan Arief Patanga, arena politik di Poso ditandai dengan meningkatnya peranan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) setempat sebagai partai oposisi yang mendukung perlawanan rakyat di basis-basis ekonomi yang dirambah oleh proyek-proyek pembangunan yang direstui oleh pemerintah Kabupaten Poso, sejak pertengahan 1990-an. Meningkatnya gerakan oposisi itu direspons oleh Arief Patanga dengan memobilisasi preman-preman untuk berdemonstrasi mendukung rezimnya dan menentang opoisi PDI. Kebetulan, pendukung PDI kebanyakan berasal dari kelompok etnis Minahasa dan suku-suku asli yang mayoritas beragama Kristen, yakni Pamona dan Mori. Sedangkan preman-preman yang dikerahkan untuk menghadapi oposisi rakyat setempat, kebanyakan berasal dari anakbuah kroni-kroni Bupati yang berasal dari suku Bugis dan Makassar.
a.4. Pelestarian kepentingan oligarki Arief Patanga:
Pelestarian kepentingan oligarki Arief Patanga, Bupati Poso dari tahun 1989 s/d 1999, sesungguhnya merupakan faktor yang paling dominan di balik meletusnya kerusuhan Poso gelombang pertama (Desember 1998) dan kedua (April 2000). Seperti yang telah disinggung di atas, korupsi telah sangat merasuk dalam pemerintahan daerah di Kabupaten Poso, dirintis oleh pejabat-pejabat asli yang beragama Kristen. Tapi di bawah Arief Patanga, korupsi itu mencapai puncaknya. Mengikuti jejak Soeharto di Jakarta dan Gubernur Azis Lamadjido di Palu, Patanga juga menerapkan nepotisme dalam birokrasi Kabupaten Poso. Isterinya, Ny. Rahmah Patanga-Malewa diangkatnya menjadi Kepala Bagian Kepegawaian dan seorang adiknya, Agfar Patanga, diangkatnya menjadi Kepala Bagian Pembangunan. Dibantu oleh dua orang kunci di birokrasi Poso, banyak proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Poso – yang waktu itu masih mencakup Kabupaten Morowali sekarang – jatuh ke tangan pemborong-pemborong yang masih termasuk marga Patanga atau Malewa (Aditjondro 2003: xxviii-xxix).
Untuk menutupi jaringan korupsinya, lapis kedua pemborongan proyek-proyek PU dibagi-bagikan oleh sang adik, Agfar Patanga, kepada kroni-kroni yang dapat diajak berlindung di balik selubung ICMI Poso yang diketuai oleh sang bupati sendiri. Kroni-kroni itu, yang kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan dan belum satu generasi bertempat tinggal di Poso, kemudian juga kecipratan dana Kredit Usaha Tani (KUT) yang lebih banyak dipakai untuk kampanye kepresidenan Adi Sasono, Menteri Koperasi & UKM di bawah Presiden Habibie, dengan menggunakan kendaraan Partai Daulat Rakyat (PDR).
Jejaring korupsi (cabal) Arief Patanga juga meliputi segelintir anggota DPRD Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi Tengah, yang kemudian ikut memicu kerusuhan Poso gelombang pertama dan kedua. Ikut menggenapi jejaring korupsi itu adalah seorang pengusaha keturunan Tionghoa, Steven Lianto, dan seorang pengusaha keturunan Arab yang sudah bermukim di Jakarta, Hasan Nazer, yang memasok komponen senjata SS1 ke PT Pindad, pabrik senjata milik Angkatan Darat. Kebetulan ibu Hasan juga berasal dari marga Malewa, sama seperti marga isteri Arief Patanga (Aditjondro 2003: xxix-xxxii; wawancara dengan Hasan Nazer di Jakarta; sumber-sumber lain).
Nah, ketika tiba giliran Patanga untuk mengorbitkan calon pengganti Sekwilda dan Bupati, ia selalu mengajukan calon-calon yang beragama Islam. Ini bertentangan dengan apa yang sudah jadi konsensus tidak tertulis di Kabupaten Poso, yakni bahwa untuk menghormati keragaman agama di daerah itu, jabatan bupati selalu dirotasi antara tokoh Kristen dan Islam. Apalagi Sekwilda Kabupaten Poso, Yahya Patiro, seorang birokrat beragama Kristen dan asli Poso, sudah didrop oleh Gubernur Azis Lamadjido ketika menyetujui pengangkatan Arief Patanga sebagai bupati, agar dipersiapkan untuk menjadi bupati Poso berikutnya.
Dalam situasi ketegangan politik itulah meletus kerusuhan pertama antara tanggal 24 s/d 28 Desember 1998. Selama kerusuhan itu beredar selebaran gelap yang menuduh sejumlah tokoh Kristen berusaha melakukan kudeta terhadap Bupati Arief Patanga. Setelah diselidiki oleh Laboratorium Forensik Polri di Makassar, ternyata selebaran itu ditulis tangan oleh Agfar Patanga, adik sang bupati.
Selebaran itu adalah hasil pertemuan kelompok Agfar Patanga dan sahabat-sahabatnya, yang berapat di rumah jabatan Bupati Patanga pada tanggal 22 Desember 1998. Hadir dalam pertemuan itu Agfar Patanga sendiri serta sejumlah tokoh Muslim asal Gorontalo dan Sulawesi Selatan, yakni Adnan Arsal, Hasan Lasiata, Nani Lamusu, Maro Tompo, Daeng Raja, Mandor Pahe, Atmajaya Marjun, dan Mukhtar Lapangasa. Kelompok ini kemudian mengformalkan dirinya menjadi Forum Silaturahmi & Perjuangan Umat Islam (FSPUI) yang kemudian berganti nama menjadi Forum Pembela Umat Islam (FPUI) yang dipimpin oleh Adnan Arsal sebagai ketua dan Hasan Lasiata sebagai sekretaris. Tanggal 24 Desember 1998, selebaran itu sudah siap untuk diedarkan. Tinggal menunggu momen politik yang tepat, yang diciptakan dengan memanipulasi perkelahian yang lumrah di antara dua orang pemuda yang kebetulan berbeda agama, menjadi peristiwa pelecehan umat Islam yang dipicu oleh minuman keras.
Gara-gara selebarannya, Agfar Patanga diperiksa oleh polisi, di tengah-tengah iklim politik di kota Poso yang makin memanas akibat intimidasi kelompok pendukungnya yang mengancam akan membuat kerusuhan lagi apabila Agfar tidak dibebaskan. Keadaan tidak menentu itu berjalan terus sepanjang tahun 1999, selama jabatan Bupati untuk sementara diisi oleh seorang tentara, Haryono, yang sebelumnya adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan juga eks Danrem 132/Tadulako.
Pemilihan Bupati yang definitif baru terlaksana tanggal 30 Oktober 1999, di mana Bupati Poso sekarang, Abdul Muin Pusadan, aktivis Golkar yang sebelumnya PR III Universitas Tadulako, ‘terpilih’ dengan suara terbanyak tapi juga dengan sogokan tertinggi kepada para anggota DPRD Kabupaten Poso, yakni Rp 20 juta seorang. Orang ini ternyata juga sudah membuat deal dengan bupati sebelumnya, sebab ia tetap mengikutsertakan Agfar Patanga dalam jajaran birokrasi Pemda Poso sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Poso. Baru sesudah Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada Agfar pada tanggal 20 November 2000, Bupati Muin Pusadan membebastugaskan Agfar Patanga dari jabatannya. Tapi demi perimbangan, rupanya, seorang pejabat yang beragama Kristen juga dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Kecamatan Lage, tanpa alasan yang jelas (Damanik 2003: 12-21; sumber-sumber lain).
Celakanya, di bawah kepemimpinan Muin Pusadan, kerusuhan Poso gelombang kedua meletus pada tanggal 17-21 April 2000. Kerusuhan ini meletus pada saat proses pengadilan terhadap Agfar Patanga masih sedang berjalan, dan pada saat proses pemeriksaan terhadap para manipulator dana KUT sedang dijalankan oleh Kapolres Poso, Letkol (Pol) Deddy Woeryantono. Meninggalnya tiga orang demonstran akibat tembakan peluru tajam Brimob yang dikerahkan untuk mencegah massa membakar gereja GKST terbesar kedua di kota Poso kemudian digunakan sebagai alat propaganda untuk menuntut pencopotan Kapolres yang tegas itu, selain menuntut penarikan Brimob dari kota Poso. Walhasil, Deddy Woerjantono ditarik ke Jakarta, Agfar Patanga sementara itu sudah dikenakan tahanan luar, dan pemeriksaan manipulasi dana KUT terbengkalai (Tengko t.t.; Aditjondro 2003: xxxiv-xxxv).
Patut juga dicatat, bahwa seperti kerusuhan gelombang pertama, kerusuhan gelombang kedua ini juga tidak terlepas dari persiapan yang dibuat oleh tokoh-tokoh yang tergabung dalam FSPUI. Sebab pada hari Jumat, 14 April 2000, sesudah salat Jumat, diadakan pertemuan di Mesjid Agung Baiturahman Poso yang dipimpin langsung oleh Adnan Arsal dan Hasan Lasiata. Hadir juga dalam pertemuan itu Maro Tompo, Daeng Raja, Mandor Pahe, Kasmad Lamuka, Mukhtar Lapangasa, Yusup Dumo, Ahmad Laparigi, dan sejumlah anggota RISMA Baiturahman.
Dalam pertemuan itu disepakati untuk membuat kerusuhan guna menuntut pembebasan Agfar Patanga dari tuduhan, pengangkatan Damsyik Ladjalani sebagai Sekretaris Kabupaten Poso, serta pencopotan Yahya Patiro dari jabatannya sebagai Asisten IV Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah. Begitu menurut wawancara Syafrudin Lukman dengan suratkabar Morowali Pos, tanggal 25 April 2000 (Damanik 2003: 25-29).
Sejak saat itulah, saling menyerang dan saling membakar rumah ibadah mulai semakin gencar di antara kedua komunitas. Selama bulan Mei 2000, kompleks Gereja Katolik Santa Theresia di Kelurahan Moengko dibakar oleh massa Muslim, dan sebaliknya kompleks pesantren Walisongo di Desa Sintuwulemba, sembilan kilometer sebelah selatan kota Poso dibakar oleh massa Kristen.
Sekarang, ke mana larinya mantan Bupati Poso yang adik dan para kroninya ikut mencetuskan kerusuhan Poso gelombang pertama dan kedua? Juga, berapa besar dana publik – khususnya kekayaan rakyat Poso – yang telah dibawanya hijrah ke luar Poso? Ternyata, selesai masa jabatannya, Arief Patanga membeli tanah di kompleks Pepabri di daerah Gedong Kuning, Yogyakarta. Maklumlah, ia cukup mengenal Yogya dari masa kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di sana. Setelah merubuhkan rumah tua di tanah itu, dibangunnya rumah baru senilai Rp 500 juta, dan memboyong isteri dan empat dari lima orang anaknya ke sana. Di sana ia membangun empat tempat pondokan mahasiswa. Salah satunya, yang terbesar, mungkin, punya 40 kamar di daerah Condong Catur senilai Rp 300 juta. Selain usaha bersama buat keluarga Patanga di Yogya itu, masing-masing anak diberinya aset-aset untuk berbisnis.
Dewi, anak perempuannya yang tertua, dibelikannya butik pakaian Muslim di Jalan Sultan Agung di daerah Pakualaman. Setelah menikah, dibelikannya Dewi rumah di perumahan Green House. Total nilai butik dan rumah Dewi sekitar Rp 400 juta. Belakangan ini, barangkali untuk mengurangi sorotan masyarakat Poso di Yogya, Dewi dan suaminya telah pindah ke Palu, tinggal di rumah keluarga Patanga di Talise, di mana suami Dewi membuka bisnis telepon seluler.
Taufik dan Hidayat, kedua anak kembar Patanga, juga dibelikannya aset berbisnis. Taufik dibelikannya ruko di Jalan Taman Siswa, juga di daerah Pakualaman, di mana ia membuka penyewaan player dan CD, laundry dan wartel. Nilai totalnya sekitar Rp 200 juta. Hidayat dibelikannya ruko di daerah Kali Mambu seharga Rp 150 juta. Gafur, anak bungsu Patanga, telah mendirikan sebuah production house, Orange Digital Video, di Jalan Timoho No. 32, Yogyakarta. Rumah produksi film-film pendek untuk disiarkan di televisi, dan telah mendapatkan order kecil-kecilan.
Seluruh keluarga Patanga di Yogya dibelikannya empat buah mobil, yakni sebuah mobil Toyota Starlet 1999 senilai Rp 120 juta, sebuah mobil Toyota Kijang 1998 senilai Rp 80 juta, sebuah Toyota Corolla 2000 senilai Rp 140 juta, dan sebuah Mazda Van Trend 1996 senilai Rp 60 juta. Sebelumnya, Patanga sudah memperoleh hadiah rumah kayu yang lumayan mewah di Jalan Yos Sudarso No. 16 senilai Rp 100 juta, di kawasan Pantai Talise, Palu, dari seorang kontraktor di Poso. Rumah itu kini dihuni oleh putra sulung Patanga, Fahmi, satu-satunya anaknya yang menjadi pegawai negeri dan bekerja di kantor Gubernur Sulteng. Selain untuk kesejahteraan di dunia, Patanga tidak lupa memikirkan kesejahteraan keluarga besarnya di akhirat. Antara tahun 1999-2000, ia mensponsori sepuluh orang anggota marga isterinya (Malewa) dan 15 orang anggota marganya sendiri (Patanga) untuk naik haji (Aditjondro 2004a).
Belakangan ini, mungkin karena sudah merasa disoroti oleh masyarakat Poso di Yogya, Patanga mulai mengalihkan aset-asetnya ke luar Yogya. Bersama bekas Gubernur Sulteng, Banjela Paliuju, Patanga menanam modal dalam sebuah industri mebel kayu jati di Jepara. Dewi menjual butiknya di Yogya, dan bersama suaminya pindah `ke Palu, di mana suaminya membuka bisnis ponsel di rumah milik keluarga Patanga di Talise.
Semua yang telah dibeberkan di atas adalah kekayaan keluarga besar Arief Patanga yang tampak, yang nilainya mendekati Rp 2 milyar. Berapa lagi kekayaan Arief Patanga yang tidak tampak, alias yang tersembunyi diam-diam di rekening-rekening banknya? Sebab tidak mungkin seseorang membeli sekian banyak rumah dan mobil mewah, kalau tidak ada dana yang minimal sama banyaknya di bank untuk biaya pemeliharaan aset-aset yang tampak itu. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa Arief Patanga telah meninggalkan Poso, tidak hanya dengan kerusuhan, tapi juga dengan deposito beberapa milyar rupiah di bank.
a.5. Warlordism Ambo Dae di Morowali:
Tana Mori, yang sekarang sudah menjadi bagian dari Kabupaten Morowali, pada awalnya tidak tersentuh oleh kerusuhan di kota Poso, walaupun banyak orang Mori dari kota Poso mengungsi ke sana. Baru di bulang Agustus 2002, Morowali mulai ikut tersentuh kerusuhan itu, dengan penyerangan ke desa-desa Peleru dan Mayumba, tanggal 13 dan 15 Agustus.
Agak berbeda dengan konteks di Poso, gejolak sosial di Morowali, khususnya di Tana Mori, sangat dipengaruhi oleh figur seorang warlord di Kecamatan Mori Atas bernama Ambo Dae. Tokoh asal Sulawesi Selatan ini pada awalnya adalah anak buah pemimpin DI/TII, Kahar Muzakkar, yang hijrah ke Sulawesi Tengah untuk melarikan diri dari pengejaran TNI. Bersama anak buahnya ia menetap di Desa Peleru Bugis, waktu Desa Peleru Bugis dan Desa Peleru Pamona belum dilebur oleh pemerintah.
Selama puluhan tahun menetap di Kecamatan Mori Atas, Ambo Dae berhasil membangun kerajaan bisnisnya, yang pada awalnya bermula dari penangkapan dan penjinakan sapi-sapi liar yang banyak berkeliaran di padang rumput Mori Atas. Dari situ bisnisnya melebar ke perkebunan coklat dan penyewaan mobil truk, dengan mempekerjakan orang-orang Bugis. Rumah-rumah mewahnya tersebar di Desa-Desa Tomata dan Taliwan. Ia beristeri tiga orang, Bugis dan Mori, dan karena telah naik haji, status sosialnya semakin meningkat di kalangan migran Bugis di Tana Mori.
Setelah Desa Peleru Bugis dilebur dengan Desa Peleru Pamona, masyarakat majemuk yang terdiri dari kelompok etnis Bugis (Muslim) serta kelompok etnis Pamona dan Mori (Kristen) semuanya berada di bawah pengaruh Ambo Dae dan klannya. Soalnya, Kepala Desa Peleru, seorang Pamona yang beragama Kristen, dijadikan kaki tangannya dalam menjarah hasil hutan secara illegal. Pelanggaran hukum itu mendapat beking dari Babinsa di Peleru. Pengolahan kayu hasil curian itu dilakukan di bukit Korontouw, yang menjadi basis perusuh waktu penyerangan ke Beteleme tanggal 10 Oktober 2003.
Klan Ambo Dae tidak cuma punya pengaruh di dataran Mori (Morowali), tapi juga di kota Poso. Beberapa orang kerabatnya punya posisi yang cukup berpengaruh di komunitas Muslim di sana, selama kerusuhan-kerusuhan yang lalu. Mereka itu adalah seorang kemanakan Ambo Dae bernama dokter gigi Fatimah, yang akrab dipanggil dokter Timang, dulu Kepala Puskesmas Tentena dan sejak 2001 dipindah menjadi Kepala Puskesmas di Kelurahan Lawanga; Syamsudin Gomo yang tinggal di Kelurahan Bonesompe; dan Rapriani Ndobe, Kepala Bagian Keperawatan RSU Poso.
Kembali ke jaringan Ambo Dae di Morowali. Bisnis kriminal klan Ambo Dae mulai menjadi persoalan, ketika kaki tangan sang raja ternak pergi mencuri sapi milik masyarakat Desa Kamba di Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso. Masyarakat desa itu termasuk anak suku Onda’e, yang masih tebal budaya perangnya, mula-mula hanya menggerutu, karena tidak berani melawan Ambo Dae dan anak buahnya. Baru setelah orang Onda’e memelopori serangan balasan ke kota Poso, masyarakat Kamba pun mulai melawan. Sapi-sapi mereka yang dulu dicuri oleh anak buah Ambo Da’e mereka rampas kembali, dengan bantuan milisi Onda’e. Dalam keadaan terdesak, Ambo Dae melarikan diri untuk menyusun kekuatan di Kolonedale.
Bekas gerilyawan DI/TII yang merasa terhina itu, kemudian melakukan aksi balasan. Pasukannya dipusatkan di bukit Korontou, tempat salah satu rumah dan pusat penggergajian kayu Ambo Dae. Dari Korontou pasukan yang dipimpin anak sulung Ambo Dae, Abidin, menyerang dan membakar rumah-rumah masyarakat Kristen di Desa Peleru dan Mayumba di Kecamatan Mori Atas, di hari Selasa dan Kamis, 13 dan 15 Agustus 2002. Serangan yang salah alamat, sebab konflik yang sesungguhnya adalah antara orang Kamba dan anakbuah Ambo Dae.
Dalam serangan ke Peleru dan Mayumba, ada indikasi bahwa dokter Timang membantu penyaluran amunisi dari kota Poso ke Morowali. Menjelang penyerangan ke Peleru dan Mayumba di bulan Agustus 2002, seorang narasumber di Tentena mengalami kejadian yang dapat dijadikan indikasi penyaluran amunisi untuk serangan-serangan itu. Pada hari Jumat, 9 Agustus 2002, narasumber ini naik bus Tomohon Indah dari Makassar ke Poso, yang waktu itu hanya berisi sembilan orang penumpang.
Salah seorang penumpang membawa sekitar 20 peti, memenuhi lorong di antara penumpang. Masing-masing peti sangat berat, sehingga harus diangkat dengan susah payah oleh empat orang laki-laki dewasa ke atas bus tersebut. Menurut penumpang bus yang misterius itu, barang-barang bawaannya adalah kiriman untuk RSU Poso, yang akan diserahkannya ke dokter Timang. Tiga dan lima hari kemudian, Desa-Desa Peleru dan Mayumba diserang. Empat orang meninggal dunia di Mayumba. Dua regu aparat keamanan yang melakukan penyisiran di desa itu menemukan dua butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm. Begitu menurut narasumber lain di Palu.
Sebagai reaksi atas penghancuran rumah-rumah masyarakat Kristen di Peleru dan Mayumba, milisi Onda’e yang sedang mengikuti padungku (pesta syukuran panen) di Kamba menyerang perkampungan orang Bugis dari Tiwa’a sampai Ensa di Kecamatan Mori Atas, termasuk di Desa Tomata, ibukota kecamatan. Berpakaian hitam-hitam, milisi Onda’e itu menghancurkan dan membakar rumah-rumah orang Bugis dan mengusir semua orang Bugis yang mereka temukan.
Setelah kejadian itu, untuk menghindarkan kemungkinan balas dendam kelompok Kristen barangkali, Timang menyingkir ke rumah pamannya, Syamsuddin Gomo, di Taripa. Ibukota Kecamatan Pamona Timur itu, penduduknya kebanyakan termasuk anak suku Onda’e, yang ikut melakukan pembalasan dendam atas penyerangan desa-desa Peleru dan Mayumba. Setelah rumah Gomo dibakar oleh massa Onda’e, Timang lari lagi ke Kolonedale ke rumah kerabatnya yang lain, Haji Majid. Dari sana ia terus lari ke Makassar dengan menumpang kapal Tilongkabila.
Sedangkan Syamsuddin Gomo, tetap bertahan di Kolonedale sebagai manajer CV Tunggal Utama (Fakta, Sept. 2003: 18). Perusahaan kontraktor itu bergerak dalam pembangunan jalan dan bangunan serta pengadaan barang-barang dinas di Kolonedale, sementara di Poso bergerak dalam jual-beli beras.
Sementara itu, Ambo Dae semakin sakit hati dan kembali menyusun kekuatan di Kolonedale. Aparat keamanan yang sudah mengetahui lokasi persembunyiannya tidak berani – atau tidak mau – menangkap Ambo Dae untuk memproses serangan anakbuahnya ke Peleru dan Mayumba, yang melahirkan serangan balasan itu. Pjs. Bupati Morowali, Tato Masituju malah mencoba merangkul pemuka masyarakat Bugis itu dengan memberinya kesempatan terlibat dalam proyek-proyek Kabupaten, dengan jaminan tidak melakukan kerusuhan di Peleru.
Berbekal proyek-proyek itu, Ambo Dae kemudian menikahi seorang gadis Mori yang belum genap 20 tahun usianya, sebagai isteri keempatnya. Sebelumnya ia sudah memiliki tiga orang isteri dari suku Bugis dan Mori.
Belum jelas apakah Ambo Dae atau anak buahnya ikut terlibat menyiapkan atau membiayai serangan perusuh di Beteleme, 10 Oktober lalu. Yang jelas, ia sekarang sudah masuk D.P.O. Polda Sulteng, mungkin karena sebagian perusuh itu melarikan diri ke Korontou. Juga, ada informasi bahwa awal November lalu segerombolan orang di bawah pimpinan Abidin masih bertahan dan sedang siap siaga di Korontou.
(b). Kepentingan-kepentingan nasional:
b.1. Pemutihan korupsi Adi Sasono dan jaringan PDRnya:
Ketika menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di masa kepresidenan B.J. Habibie, anak buah Adi Sasono dari Partai Daulat Rakyat (PDR) memanipulasi trilyunan rupiah dari program JPS (Jaringan Pengaman Sosial) dan KUT (Kredit Usaha Tani) untuk mendukung kampanye kepresidenan sang Menteri. Dari dana KUT sendiri antara Rp 8,3 dan 8,4 trilyun tidak sampai ke tangan petani. Hasil audit BPKP menunjukkan bahwa penyaluran KUT sepanjang tahun 1998-199 hanya 39,74% yang berhasil.
Di Kabupaten Poso dan Morowali, antara tahun 1998-1999, ada Rp 5,7 milyar yang ditunggak oleh empat lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Poso, yang sebagian besar dipimpin oleh pengurus PDR Wilayah Sulawesi Tengah dan Cabang Poso. Ketika Kapolres Poso waktu itu bermaksud menahan tokoh-tokoh PDR itu untuk mengusut korupsi dana KUT itu, mereka terjun memprovokasi massa pemuda di kota Poso, sehingga meletuslah kerusuhan Poso gelombang kedua di bulan April 2000 (Aditjondro 2003: xxix-xxxv; Aditjondro 2004a).
b.2. ICMI-nisasi birokrasi pemerintahan daerah oleh rezim Soeharto dan Habibie:
Seperti yang telah disinggung di depan, ketika Arief Patanga berusaha mendapat restu Gubernur Sulawesi Tengah, Azis Lamadjido, untuk menjadi Bupati Poso, restu itu diberikan dengan catatan bahwa Patanga harus menyiapkan calon penggantinya dari komunitas Kristen. Untuk itu, Gubernur Lamadjido mendrop seorang birokrat asli Poso yang beragama Kristen, Yahya Patiro, sebagai Sekwilda di Poso. Begitu dijelaskan oleh Usman Sondeng, anggota DPRD Provinsi Sulteng asal Bungku (kini masuk Kabupaten Morowali), yang selama 14 tahun menduduki jabatan Kepala Biro Humas Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Ternyata, bukan Yahya Patiro yang dicalonkan oleh Arief Patanga untuk mengganti dirinya menjadi Bupati Poso, tapi Damsyik Ladjalani. Sebelumnya, selama masa jabatannya yang kedua, Arief Patanga gencar sekali menggeser pejabat-pejabat yang beragama Kristen dari administrasi pemerintahannya, untuk digantikan oleh pejabat-pejabat yang se daerah asal dan se iman. Sementara loyalitas mereka kepada dirinya diperkuat lewat posisi dirinya sebagai Bupati merangkap sebagai Ketua ICMI Kabupaten Poso. Kebijakan itu tidak melawan kehendak pemerintah Pusat, sebab trend itu sudah dirintis oleh Soeharto sendiri dan dilanjutkan oleh penggantinya, B.J. Habibie. Tapi dengan demikian, semakin sempurnalah marjinalisasi dan alienasi birokrat-birokrat yang beragama Kristen – dan secara etnis mewakili mayoritas penduduk asli Kabupaten Poso – di luar daerah Tojo dan Bungku dalam tampuk pemerintahan kabupaten itu.
b.3. Kepentingan aparat keamanan:
b.3.1. Pemekaran Kodam dan Batalyon:
Era kepresidenan B.J. Habibie sejak Mei 1998 s/d September 1999, tidak saja ditandai dengan berhembusnya angin kebebasan bagi pers dan partai politik, tapi juga diimbangi dengan keinginan militer untuk mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi mereka. Begitu diangkat sebagai Menhankam merangkap Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Wiranto tidak saja merintis pelepasan Polri dari ABRI, yang kemudian berubah sebutannya menjadi TNI, tapi juga mengumumkan rencananya untuk menghidupkan kembali Kodam-Kodam yang sudah ditutup di zaman Benny Murdani. Berarti, jumlah Kodam yang sudah menciut dari 17 menjadi sepuluh, akan dikembalikan menjadi 17 lagi.
Itulah kebijakan Wiranto yang kemudian dikenal dengan istilah “pemekaran Kodam”. Untuk memekarkan Korem-Korem yang mau dikembalikan menjadi Kodam, perlu ada penempatan pasukan-pasukan di sana, yang dapat ditingkatkan statusnya dari pasukan sementara alias BKO menjadi pasukan organik. Untuk itu, gangguan keamanan di daerah-daerah itu harus dilanggengkan. Strategi ini sudah berhasil dijalankan di Kepulauan Maluku, di mana setahun sesudah meletusnya konflik di Ambon, Korem Pattimura telah dimekarkan menjadi Kodam (Aditjondro 2001: 120).
Walaupun Wiranto sudah lengser dari jabatan kemiliterannya, tidak berarti bahwa rencana pemekaran Kodam itu sudah ditinggalkan. Hari Selasa, 15 Oktober 2002, di depan peserta jambore nasional Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jendral Ryamizard Ryacudu menegaskan: “Saya tidak akan membubarkan Kodam. Bahkan, kalau bisa ditambah” (Kompas, 17 Okt. 2003).
Kenyataannya, kalangan militer berulangkali maju mundur tentang rencana menghidupkan kembali Kodam XIII Merdeka yang berpusat di Manado. Namun setahun sesudah penandatanganan Deklarasi Malino, rakyat Sulawesi Tengah mendapat ‘hadiah Tahun Baru’ berupa penegasan Danrem 132/Tadulako bahwa TNI/AD akan segera membentuk satu batalyon baru, Yon 714 Sintuwu Maroso yang berkedudukan di Poso. Menurut Danrem 132/Tadulako waktu itu, batalyon baru dengan ketiga kompinya akan bertugas menangani masalah keamanan sepanjang pesisir pantai timur Sulawesi Tengah. Termasuk menjaga keamanan daerah pertambangan migas Senoro-Tiaka, yang terbentang dari Kecamatan Batui di Kabupaten Banggai s/d terumbu karang Tiaka di Teluk Tomori, Kabupaten Morowali, yang akan dieksploitasi oleh Pertamina bersama PT Exspan Tomori Sulawesi milik pengusaha politikus PDI-P, Arifin Panigoro.
Dengan pembentukan batalyon baru itu, Provinsi Sulteng dengan luas wilayah lebih kurang 68 ribu km persegi akan dijaga dua batalyon TNI/AD, yakni Yon 711/Raksatama di Palu yang menjaga keamanan di wilayah yang terentang dari Kabupaten Buol dan Toli-Toli di Utara dan Yon 714/Sintuwu Maroso di Poso, yang menjaga keamanan di daerah Sulawesi Timur. Kedua batalyon itu tetap berada di bawah koordinasi Kodam VII/Wirabuana di Makassar (lihat Aditjondro 2004b).
Untuk mewujudkan kehadiran batalyon baru itu telah dipersiapkan tanah seluas 2,5 hektar di Kelurahan Ranonuncu di perbatasan selatan kota Poso. Di lokasi itu akan berdiri markas batalyon lengkap dengan barak-barak yang akan ditempati 747 personil Angkatan Darat, yang akan menjaga keamanan Poso secara permanen. Selain markas batalyon baru, akan dibangun juga markas Kompi A di Luwuk (ibukota Kabupaten Banggai), markas Kompi B di Kolonedale (ibukota Kabupaten Morowali) dan markas Kompi C di Pendolo, ibukota Kecamatan Pamona Selatan (Kabupaten Poso). Kedudukan Kompi C akan menggantikan Kompi B Batalyon 711/ Raksatama yang kini berkedudukan di Kawua di pinggiran selatan kota Poso. Untuk lokasi Markas Kompi C di Pendolo telah dibebaskan lahan seluas sembilan hektar yang tadinya milik 21 orang warga Pendolo. Biaya ganti rugi sebesar Rp 206 juta disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Poso (lihat Aditjondro 2004b).
Sementara itu, yang sudah siap dibangun dan ditempati adalah markas Kompi B di Desa Mohoni (Kecamatan Petasia), di perbatasan wilayah Mori dan Bungku. Makanya, ketika menyerang Desa Beteleme di Kecamatan Lembo, Mori Bawah, perusuh dapat bergerak dengan bebas karena para serdadu di daerah Morowali sedang dikerahkan untuk penyelesaian pembangunan markas mereka yang baru di Mohoni.
Prioritas yang diberikan kepada pembangunan markas Kompi C di Morowali dapat dianggap sebagai indicator pentingnya rencana investasi kelompok Artha Graha di mata aparat keamanan. Maklumlah, konglomerat yang dipimpin taipan muda, Tomy Winata (45 tahun), yang ikut memutar bisnis Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI/AD berencana menanam AS$ tiga juta dalam usaha tambang marmer seluas 150 hektar di Morowali. Selain tambang marmer, taipan yang sedang berperkara dengan majalah Tempo itu juga berminat mengembangkan berbagai usaha lain di Morowali, seperti pertanian, peternakan, perkebunan kelapa sawit, tebu dan jambu mete, serta pengumpulan hasil-hasil hutan seperti rotan. Untuk itu, Artha Graha berencana membangun 270 km jalan dari Kolonedale sampai ke Kendari, ibukota provinsi Sulawesi Tenggara. Ruas sepanjang 120 km dari jalan poros itu akan dijadikan jalan tol. Semua rencana itu akan membengkakkan investasi kelompok Artha Graha di pantai timur Sulawesi sampai Rp 300 milyar (Aditjondro 2004b).
Dari situ dapat kita lihat betapa kerusuhan Poso dijadikan dalih oleh fihak militer untuk memperluas kehadiran pasukannya di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, dan bukan hanya di Kabupaten Poso. Kita juga dapat melihat betapa perencanaan struktur teritorial militer berkaitan erat dengan kepentingan pengamanan usaha-usaha bermodal besar di Sulawesi Tengah bagian Timur.
b.3.2. Usaha perebutan anggaran keamanan Kabupaten Poso dan Morowali antara Polri dan Angkatan Darat:
Sementara militer menambah kehadiran pasukannya di Poso dan kabupaten-kabupaten tetangganya di Timur, fihak Polri juga tidak mau ketinggalan. Mulai akhir Juni 2003, satu kompi Brimob telah ditempatkan secara permanen di Poso. Markas mereka yang baru telah dibangun di perbukitan di daerah Mo-engko, di pinggiran barat kota Poso. Mengikuti pola penyebaran pasukan organik TNI/AD, markas-markas kompi serupa akan didirikan pula di daerah Kolonedale dan Luwuk.
Dari situ dapat kita lihat, walaupun anggaran keamanan Kabupaten Poso dan kabupaten-kabupaten tetangganya tidak meningkat, fihak militer dan polisi akan saling bertarung memperebutkan porsi terbesar dari anggaran itu. Makanya dapat diduga bahwa pelestarian konflik di daerah Poso dan Morowali juga mencerminkan persaingan di antara satuan-satuan intelijen TNI dan Polri, untuk memperebutkan hegemoni penjagaan keamanan di daerah yang kaya sumber daya alam itu. Hal itu juga mencerminkan keengganan fihak militer untuk menyerahkan penjagaan keamanan dalam negeri, khususnya di Poso, kepada aparat Polri.
Di fihak lain, Polri yang terlalu lama berada di bawah ketiak militer belum terlatih mengatasi kerusuhan tanpa menembak mati sejumlah perusuh. Maklumlah, satuan tempur Polri, yakni Brimob, terlalu terbiasa mengatasi kerusuhan dengan cara-cara militer, berkat persenjataan dan teknik tempur mereka yang juga sangat militeristik. Ini sudah terbukti tidak saja di Poso, tapi juga di daerah-daerah konflik yang lain, seperti Papua Barat dan Aceh.
Selanjutnya, karena baik Angkatan Darat maupun Polri berkepentingan untuk memperebutkan posisi hegemonis dalam penjagaan keamanan di daerah Poso dan Morowali, kedua kekuatan bersenjata itu sama-sama berkepentingan untuk memelihara keberadaan pasukan-pasukan paramiliter bersenjata di kedua daerah itu.
b.3.3. Politik “ cuci gudang” PT Pindad?
Seperti halnya di Aceh, jenis amunisi yang paling banyak beredar di Poso dan Morowali adalah peluru buatan PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad). Khususnya peluru kaliber 5,56 mm, yang dapat dipakai sebagai amunisi buat senapan otomatis jenis SS-1, yang juga buatan Pindad, dan M-16 buatan AS. Selain itu, yang banyak beredar saat-saat pertempuran sedang berkecamuk, yang ditawarkan oleh pedagang-pedagang yang tidak jelas identitasnya, adalah peluru jenis FN dan Colt buatan Pindad pula. Sebagian amunisi itu, bukanlah barang yang baru saja diproduksi. Ada juga stok lama.
Sehari setelah penyerangan perusuh ke Desa Sepe di Kecamatan Lage, pada malam Minggu, 1 Desember 2001, ditemukan satu peti peluru kaliber itu di desa itu. Pada kotak berlogo PT Pindad yang berkapasitas 1400 butir peluru ada tulisan dengan spidol, “Poso”, serta tulisan dengan cat “B”. Dari situ dapat ditafsirkan bahwa kotak peluru seberat 25 kg itu adalah jatah Kompi B Batalyon 711/Raksatama di Kawua, Poso, tapi entah bagaimana caranya, “terbawa” oleh para perusuh ke kedua desa yang naas itu.
Menurut keterangan di peti peluru itu, amunisi buatan PT Pindad bulan Maret 1989 didasarkan pada kontrak No. KJB/004/DN/M/1988, tertanggal 12 Maret 1988. Makanya masih merupakan teka-teki, bagaimana kotak peluru itu bisa sampai ke Desa Sepe di Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, lebih dari 12 tahun kemudian (lihat Aditjondro 2004b).
Selain kejadian itu, senjata dan amunisi buatan PT Pindad berulangkali dicoba untuk diselundupkan ke Poso dan Morowali (lihat Aditjondro 2004b). Ada yang lolos, ada juga yang berhasil dipergok dan disita oleh petugas, seperti kisah tertangkapnya Farihin Ibnu Ahmad alias Yasir (37) dan Siswanto Ibrahim alias Anto (26) di Pelabuhan Pantoloan, Palu, pada hari Rabu, 2 Oktober 2002, sekitar jam 12 tengah malam. Dari bagasi mereka yang baru turun dari KM Nggapulu disita sebuah peti berisi 2846 butir peluru dari beberapa kaliber Colt dan SS-1 buatan PT Pindad, 15 pucuk senjata api dari beberapa jenis (SS, Baretta, dan FN), tiga buah sangkur M-16 berserta sarungnya, serta empat buah teleskop jenis Rifle Scope Narconia buatan Jerman, tersembunyi di antara 12.942 buah petasan. Amunisi dan senjata api itu, menurut penasehat hukum Yasir dan Anto yang kini mendekam di Rutan Maesa, Palu, adalah titipan dari ‘Tarjo’ di Mapane, ibukota Kecamatan Poso Pesisir (Aditjondro 2004b).
Nah, kalau ini bukan kasus ‘korupsi biasa’, kita perlu bertanya, apakah memang ada kebijakan untuk membuang stok lama PT Pindad, dengan menyalurkannya ke daerah-daerah konflik seperti Aceh dan Poso? Khusus dalam kasus Poso, ada informasi bahwa semacam petunjuk perakitan senjata SS-1, sudah beredar di Kabupaten Poso, menjelang pecahnya kerusuhan gelombang kedua dan ketiga tahun 2000. Makanya, baik komunitas Muslim maupun Nasrani waktu itu, buru-buru mengerahkan bengkel-bengkel bubut dan pandai besi mereka untuk membuat senjata rakitan.
Dari situ dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar ada orang Poso, atau orang Poso yang dekat ke PT Pindad, yang membantu melariskan produk-produk Pindad – peluru dan senjata – di Poso. Karena satu-satunya orang Poso yang dikenal punya hubungan bisnis dengan PT Pindad adalah Hasan Nazer (56 th), penulis menanyakannya langsung ke Hasan Nazer di rumahnya di Jalan Cemara, Menteng, tanggal 29 Oktober 2003.
Hasan Nazer dengan tenang tapi tegas menyangkal segala tuduhan ke alamat diri maupun saudara-saudaranya bahwa mereka pernah terlibat dalam pemasokan senjata atau amunisi ke Poso. Ia membenarkan bahwa perusahaan pengecoran logamnya punya kontrak dengan PT Pindad. Tapi itu terbatas pada pembuatan tiga komponen SS-1, yakni pelatuk, hammer, dan vicier. “Nilai order Pindad itu tidak seberapa. Saya kerjakan hanya supaya dapat lisensi dari Pindad bahwa perusahaan saya mampu membuat komponen-komponen yang memerlukan presisi yang begitu tinggi. Dengan lisensi itu mudah dapat order dari perusahaan-perusahaan di Eropa”, begitu keterangan Hasan Nazer kepada penulis.
Jadi, siapa yang harus bertanggungjawab atas politik “cuci gudang” yang diterapkan PT Pindad di Poso dan juga di Aceh? Bukankah ini tanggungjawab Kepala Staf Angkatan Darat juga, yang secara ex officio merupakan Komisaris Utama PT Pindad? Atau kalau mau ditarik ke belakang, bukankah ini juga merupakan tanggungjawab B.J. Habibie juga, yang sebagai Kepala Badan Pengendali Industri Strategis (BPIS), yang membawahi PT Pindad, membiarkan pabrik itu mengalami kelebihan produksi peluru, yang tidak dimusnahkan, tapi dibiarkan “bocor” ke daerah-daerah konflik?
b.3.4. Kolusi aparat keamanan dengan kelompok-kelompok paramiliter setempat:
Sama misteriusnya seperti sumber dan jalur penyebaran amunisi dan senjata Pindad itu adalah jaringan organisasi yang memobilisir penyerangan, bom, dan penembak-penembak misterius di Poso dan Morowali. Bahkan belakangan wilayah gangguan keamanan a la Poso sudah menyebar pula ke Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai. Makanya cukup mengejutkan ketika dalam kunjungannya ke Poso, pasca penyerangan ke Beteleme dan Poso Pesisir, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa sejumlah “kamp teroris” sudah ditemukan di pedalaman Poso. “Lokasi-lokasi itu dijadikan pusat latihan yang terorganisasi untuk aksi kekerasan dan kekacauan baru di daerah itu”, katanya di Palu. Ia menamai para perusuh itu sebagai “gerombolan pengacau keamanan (GPK)”, yang terdiri dari orang luar Poso yang bekerjasama dengan penduduk lokal (Suara Pembaruan & Manado Post, 17 Okt. 2003).
Orang yang semestinya paling tahu tentang komplotan itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendroprijono secara terpisah memastikan bahwa pelaku kerusuhan di Poso (dan Morowali) merupakan pihak-pihak lama yang sempat bertikai dua tahun lalu (maksudnya, tahun 2001). Tapi mengenai dugaan keterlibatan fihak militer, yang diindikasikan dengan penemuan senjata dan amunisi standar TNI, Hendroprijono meminta semua fihak untuk tidak berspekulasi. Sebab kalau berspekulasi, begitu menurut Kepala BIN, keadaan bisa menjadi tidak baik (Manado Post, 15 Okt. 2003).
Di Palu sendiri, Danrem 132/Tadulako, Kol. (Inf.) M. Slamet dan Kapolda Sulteng, Brigjen M. Taufik Ridha juga sibuk cuci tangan. Menurut Kapolda, aparat tak terlibat dalam kerusuhan di Poso, sedangkan menurut Danrem, bukan hanya TNI/AD yang menguasai amunisi buatan Pindad, tapi juga angkatan-angkatan lain dan Polri (Suara Pembaruan, 21 Okt. 2003).
Nah, kalau sekarang sanggahan Hendroprijono, Slamet dan Taufik Ridha kita hadapkan dengan pernyataan Yudhoyono bahwa ada “pusat latihan pengacau” alias “kamp-kamp teroris” di pedalaman Poso, masihkah kita bisa berbicara tentang ketidakterlibatan aparat dalam “memelihara” kelompok-kelompok perusuh itu? Bedanya mungkin hanyalah, bahwa ada satuan atau “oknum” militer atau polisi yang aktif terlibat dalam pelatihan kelompok-kelompok itu. Ada pula satuan atau “oknum” militer atau polisi yang sengaja “membuang muka” saat kelompok perusuh itu sedang menuju ke tempat latihan mereka, atau ke tempat operasi mereka. Sedangkan senjata dan amunisi, begitu pula sepatu lars, seperti terbukti di Timor Lorosa’e dan Aceh, dapat dibeli dari militer atau polisi yang korup.
Tempat-tempat latihan tempur buat kelompok bersenjata terlatih, menurut sumber-sumber penulis di Poso dan Morowali, memang ada dan tersebar di tiga tempat. Kalau dulu lebih terkonsentrasi di daerah Tojo, yang kini masuk Kabupaten Tojo Una-una, belakangan ini lebih bergeser ke Kecamatan Poso Pesisir. Khususnya di atas Desa Tokorondo serta di Pada Lembara, dataran tinggi dekat Desa Pinedapa. Namun tempat latihan di daerah Tojo-Ampana masih tetap berfungsi, khususnya untuk memudahkan operasi ke kawasan Mori Atas dan Mori Bawah di Kabupaten Morowali.
Lalu, untuk memudahkan melarikan diri melintasi perbatasan ke Sulawesi Selatan, hutan sekitar Desa Pandajaya yang dihuni transmigran dari Pulau Lombok (NTB), dekat Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, juga merupakan tempat latihan bagi kelompok-kelompok militan. Mereka ini berafiliasi dengan Lasykar Jundullah di Sulawesi Selatan dan ke Ambo Dae, ex-anak buah Kahar Muzakkar yang jadi raja ternak di Mori Atas. Serangan-serangan ke Pendolo, biasanya dilancarkan dari situ (ICG 2002: 20; sumber-sumber lain).
Tanpa membongkar tempat-tempat latihan itu, dan tanpa membongkar jaringan tidak resmi antara kelompok-kelompok paramiliter itu dengan berbagai kesatuan dan oknum militer dan polisi, rakyat Poso dan Morowali akan tetap hidup dalam bayang-bayang ketakutan, karena sewaktu-waktu bom bisa meledak, pistol atau senapan penembak misterius menyalak, dan gerombolan perusuh menyerang saat orang sedang tidur lelap.
FIHAK-FIHAK YANG DIUNTUNGKAN DARI PELESTARIAN KONFLIK DI DAERAH POSO DAN MOROWALI:
(a). Aparat keamanan Polri dan TNI, termasuk satuan-satuan intelijen dan Kepala Badan Intelijen Negara:
Dari sudut makro, penempatan semakin banyak personil TNI/AD dan Polri di daerah Poso dan Morowali, berarti semakin besar dana operasi yang harus disediakan buat mereka. Semakin besar dana operasinya, semakin banyak yang dapat dikorupsi dari dana operasi tersebut. Belakangan ini, jumlah uang operasi per anggota sudah ditingkatkan menjadi Rp 20 ribu per hari, yang mencakup uang saku dan uang lauk pauk, yang secara normal dibayarkan sepuluh hari sekali. Uang operasi itu dimanfaatkan oleh anggota untuk makan di warung, terutama mereka yang bertugas di pos-pos penjagaan di tepi jalan raya. Sedangkan mereka yang bertugas di desa-desa, memberikan uang kepada orang kampung untuk memasakkan makanan bagi mereka. Itu terjadi misalnya di Kelurahan Madale di Kecamatan Poso Kota, menurut pengamatan seorang narasumber penulis, awal November lalu.
Dalam prakteknya, tentara dan polisi yang bertugas di pedalaman Poso tidak sabar untuk menerima uang operasi mereka sepuluh hari sekali. Mereka lebih senang menerima uang operasi mereka sebulan sekali. Di situlah uang operasi mereka disunat sampai 16 persen, sebab uang operasi yang diambil setiap 30 hari sekali, yang semestinya berjumlah Rp 600 ribu seorang, biasanya hanya diterimakan Rp 500 ribu seorang. Jadi untuk seorang anggota serdadu atau polisi, Bendahara atau Bagian Keuangan kesatuannya dapat menyunat Rp 100 ribu. Nah, kalau yang bertugas di Kabupaten Poso dan Morowali itu rata-rata 2000 orang setahun, maka sebulan dapat disunat Rp 200 juta, atau setahun yang dikorupsi dapat mencapai Rp 2,4 milyar!
Besarnya korupsi uang operasi itu bukannya tak diketahui oleh para prajurit dan polisi yang bertugas di lapangan. Anehnya, jarang sekali terdengar pernyataan keberatan dari bawahan terhadap tingkat korupsi sebesar itu. Memang, menurut dua orang narasumber, tahun 2001 sejumlah anggota Brimob protes ke Polda Sulawesi Tengah di Palu terhadap pemberian uang operasi mereka. Karena protes mereka yang begitu keras, akhirnya Polda menyalurkan uang operasi mereka secara utuh. Berarti, dana operasi itu sebenarnya sudah tersedia di Palu, atau, dana yang disunat entah di jenjang yang mana dapat segera dikembalikan ke Palu. Ada juga kejadian di tahun 2002, bahwa personil TNI dari Zeni Tempur (Zipur) yang bertugas di Poso datang ke kantor SAKSI (Solidaritas Anti Korupsi Sulawesi Tengah) di Palu, untuk melaporkan pemotongan uang operasi mereka.
Langkanya ekspresi ketidakpuasan para bawahan terhadap penyunatan uang operasi mereka cukup menarik. Bagaimana kita dapat menjelaskan tingkat tolerasi para bawahan sebesar itu? Apakah kepatuhan pada atasan saja dapat menjelaskan tingkat toleransi terhadap korupsi atasan mereka? Ataukah ada penjelasan lain? Menurut hemat penulis, justru di situlah fungsi bisnis kelabu militer di daerah operasi seperti Poso, yakni memberikan kompensasi pada bawahan agar tidak memprotes korupsi uang operasi oleh para atasan mereka. Dengan kata lain, para atasan mencari tambahan pendapatan dari uang operasi bawahan mereka, sementara para bawahan mencari tambahan pendapatan langsung dari rakyat setempat.
Dari studi kepustakaan, wawancara dengan sejumlah narasumber, serta pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa ada duabelas jenis bisnis kelabu militer dan polisi di Tana Poso (dan dalam beberapa hal, juga di Morowali dan Banggai), yakni (a) pemerasan secara langsung oleh ‘oknum’ berbaju seragam; (b) perlindungan bagi prostitusi terselubung; (c) sabung ayam; (d) bisnis satpam; (e) perburuan dan penyelundupan flora dan fauna langka, seperti kayu hitam dari kawasan Poso Pesisir serta ikan sogili dari Danau Poso; (f) perdagangan hasil hutan; (g) pengangkutan barang dan penumpang dengan kendaraan dinas; (h) bisnis pengawalan; (i) pungutan di pos-pos penjagaan; (j) proteksi properti milik pengusaha dan eks-pejabat tertentu; (k) bisnis proteksi operasi perusahaan-perusahaan bermodal besar; dan (l) perdagangan ilegal senjata api dan amunisi (lihat Aditjondro 2004b).
Dari pengamatan lapangan yang telah penulis lakukan bersama kawan-kawan dari Kelompok Kajian Tana Poso LOBO di Tentena, 48 pos penjagaan yang terentang sepanjang Jalan Raya Trans Sulawesi di pos Tumora dekat perbatasan Kabupaten Parimo di Barat s/d pos Watumaeta di dekat perbatasan Sulawesi Selatan, setiap hari mengutip rata-rata Rp 20 juta dari truk, bus, mobil pribadi dan penumpang yang melintas sepanjang jalan itu (lihat Aditjondro 2004b).
Taksiran itu masih lebih rendah dibandingkan dengan seorang narasumber yang biasa melintas sepanjang jalan raya dari Kolonedale (ibukota Kabupaten Morowali) sampai ke Palu, yang memperkirakan bahwa penghasilan pos-pos penjagaan sepanjang trayek itu antara Rp 35 sampai 30 juta sehari.
Sementara itu, dari kalangan petinggi dan purnawirawan TNI dan Polri, Letjen (Purn.) A.M. Hendropriyono termasuk yang punya kepentingan pribadi paling kental dengan pasang surut kerusuhan di Sulawesi Tengah, melalui bisnis anaknya, Ronny Narpatisuta Hendropriyono.
Ronny adalah komisaris dan pemegang saham PT Hardaya Inti Plantations, yang areal perkebunan kelapa sawitnya seluas 52 ribu hektar meliputi Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Perusahaan itu adalah anggota konglomerat CCM (Cipta Cakra Murdaya) milik Nyonya Hartati Murdaya, salah seorang Bendahara Golkar di era kepresidenan Soeharto. Latar belakang pelibatan Ronny Hendropriyono dalam perkebunan kelapa sawit itu mungkin ada hubungannya dengan posisi ayahnya sebagai Menteri Transmigrasi di masa kepresidenan B.J. Habibie. Apalagi kiat bisnis Ny. Hartati Murdaya begitu lihai, dengan menjadikan Azis Lamadjido, Gubernur Sulteng waktu itu, juga sebagai komisaris di perusahaan perkebunan itu.
Dengan demikian, pernyataan Hendropriyono akhir 2001, bahwa Al Qaeda dan RMS terlibat dalam kerusuhan antar agama di Poso (detik.com, 12 Des 2001), tidak dapat dilepaskan dari kepentingan perkebunan kelapa sawit anaknya di Sulawesi Tengah. Maklumlah, dengan mempertinggi citra ancaman luar negeri di Sulawesi Tengah, kehadiran pasukan TNI dan Brimob di provinsi itu dapat ditingkatkan. Pada gilirannya, pasukan-pasukan bersenjata otomatis itu dapat dimanfaatkan untuk menekan perlawanan rakyat terhadap perkebunan kelapa sawit itu, yang sudah sering menghadapi aksi-aksi petani dan aktivis lingkungan.
Bukan itu saja kepentingan bisnis keluarga Hendropriyono, yang bias tumpang tindih dengan jabatan publiknya sebagai Kepala BIN. Hendropriyono juga adalah Komisaris Utama PT Kia Mobil Indonesia, yang punya lisensi untuk mengimpor 12 jenis mobil buatan Kia Motors Corporation di Korea Selatan. Ronny Narpatisuta kembali lagi muncul di sini sebagai salah seorang direktur perusahaan itu, bersama Fayakun Muladi, anak Menteri Kehakiman di era kepresidenan B.J. Habibie. Tapi yang lebih penting adalah bahwa PT KMI ini adalah anggota Artha Graha Group milik Tomy Winata, pengusaha muda yang dekat dengan kalangan TNI/AD. Dan memang, Yayasan Kartika Eka Paksi memiliki 20% saham Bank Artha Graha, bank induk konglomerat ini.
Makanya, loyalitas Hendropriyono sebagai pejabat publik dapat diragukan. Sebab di bidang publik, dia berada di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri, malah ikut menjadi kader PDI Perjuangan. Tapi di bidang bisnis, ia berada di bawah kepemimpinan Tomy Winata.
Keterkaitan antara Hendropriyono dengan kelompok bisnis Artha Graha ini sekali lagi menimbulkan kejumbuhan dengan jabatan publiknya. Apakah selaku Kepala BIN, ia lalai mencium sepak terjang kelompok-kelompok perusuh yang mengacau keamanan rakyat di Kabupaten Poso dan tetangganya, Kabupaten Morowali? Ataukah kerusuhan-kerusuhan itu merupakan strategi yang direstui – setidak-tidaknya dibiarkan – oleh BIN, untuk melegitimasi eskalasi pasukan-pasukan TNI dan Polri, khususnya Brimob, di bekas Kabupaten Poso sebelum pemekaran itu? Apalagi karena kelompok Artha Graha kini berkepentingan untuk menambah kehadiran pasukan demi pengamanan ekspansi bisnis mereka di Kabupaten Morowali?
Soalnya, seperti yang telah disinggung di depan, konglomerat pimpinan Tomy Winata itu kini ingin membuka 150 hektar tambang marmer di Kabupaten Morowali, yang mungkin akan diperluas dengan tambang-tambang marmer di Kabupaten Poso.
Yang jelas, baik perkebunan kelapa sawit di Buol dan Toli-Toli, maupun pertambangan marmer di Morowali dan Poso, dapat diuntungkan oleh pemekaran batalyon TNI/AD yang ditempatkan di Sulawesi Tengah. Dengan dalih pengamanan Kabupaten Poso, sebuah batalyon baru, Yon 714 Sintuwu Maroso, telah dibentuk, berpusat di Poso tapi dengan satu kompi yang akan ditempatkan di Morowali. Sedangkan batalyon lama, Yon 711 Reksatama, ditugaskan untuk pengamanan Sulawesi Tengah bagian Barat, dari Buol dan Toli-Toli di Utara sampai dengan Donggala di Selatan (lihat Aditjondro 2003: xlvi). Maka sempurnalah dwifungsi Hendropriyono sebagai boss intelligence dan sebagai pengusaha (lihat Aditjondro 2004a).
(b). Aparat sipil yang terlibat dalam manipulasi aliran dana bantuan pengungsi dan dana kemanusiaan:
Kerusuhan di Poso dan Morowali telah melahirkan arus pengungsi dari kedua kabupaten itu ke daerah-daerah yang relatif aman di pedalaman Tana Poso dan Tana Mori, Palu, Bitung, dan Manado. Keberadaan ribuan pengungsi itu Sulawesi Tengah itu mengundang kucuran bermilyar-milyar rupiah dari Jakarta ke Palu, Poso dan Kolonodale, yang pada gilirannya memperkaya sejumlah pejabat dan keluarga mereka. Apalagi selain bantuan untuk pengungsi ada juga bantuan untuk penduduk yang tidak mengungsi tapi dianggap terkena dampak konflik di kabupaten-kabupaten Poso dan Morowali.
Sejak Deklarasi Malino s/d Oktober 2003, pemerintah pusat telah mengucurkan Rp 33,5 milyar dana bantuan kemanusiaan melalui Departemen Kimpraswil dan Menko Kesra Jusuf Kalla. Sedangkan Departemen Kesejahteraan Sosial telah mengucurkan Rp 68,24 milyar dari Januari 2003 s/d Mei 2003 untuk bantuan kemanusiaan di tujuh kecamatan di Kabupaten Poso dan dua kecamatan di Kabupaten Morowali (Harli 2003).
Dana sebesar itu meliputi biaya hidup (bidup ) sebesar Rp 2,5 juta/KK untuk 12.746 keluarga pengungsi, untuk jaminan hidup (jadup) sebesar Rp 1,25 juta/KK untuk 508 keluarga pegawai negeri, serta bahan baku rumah (BBR) sebesar Rp 4,5 juta/rumah berupa kayu, semen, tripleks, dan atap seng untuk 5.813 rumah pengungsi yang ingin kembali ke kampung halaman mereka. Kemudian masih ada dana lauk pauk dan beras untuk orang miskin (raskin) yang diprioritaskan untuk pengungsi pula, serta santunan sebesar Rp 2 juta/kk bagi 768 ahli waris korban kerusuhan (Harli 2003; Fajar, 12 Agustus 2003).
“Industri” pengungsi ini telah mencetak kekayaan bagi sejumlah pejabat. Makanya pemeo yang populer di Poso adalah: “Sementara pengungsi makan supermi, pejabat makan Super Kijang”. Pemeo itu sudah sampai ke telinga Menko Kesra Jusuf Kalla, sehingga ia menyodok Dinas Kesejahteraan Sosial agar tidak menjadikan pengungsi sebagai “lahan”. Itu dikatakannya di depan pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso dan Morowali di ruang Pogombo, kantor Gubernur Sulteng, Senin, 15 Desember yang lalu (Radar Sulteng, 16 Des. 2003).
Namun sekedar sindiran semacam itu tidak mempan. Seorang pejabat yang ditengarai paling banyak mengecap keuntungan dari dana bantuan buat pengungsi dan rakyat yang kena dampak konflik adalah Bupati Poso, Abdul Muin Pusadan.
Untuk memahami bagaimana Bupati Muin Pusadan memperkaya diri, keluarga dan kroninya, tidak cuma dari dana bantuan buat pengungsi, tapi juga dana pembangunan di Kabupaten Poso, kita perlu mengenal jejaring korupsi yang telah dibangunnya. Pengertian jejaring korupsi atau cabal di sini diambil dari teori korupsi William J. Chambliss, yang berpendapat bahwa korupsi sistemik seringkali merupakan bagian yang tak terpisahkan dari birokrasi pemerintahan kota di Amerika Serikat, dan merupakan satu sindikat yang meliputi empat unsur, yakni (a) birokrat, (b) politisi, (c) pengusaha, dan (d) aparat penegakan hokum, di mana kepentingan ekonomis para anggota jejaring korupsi diproteksi lewat sogokan maupun tekanan fisik terhadap setiap usaha oposisi dari warga masyarakat yang dikuasai oleh jejaring korupsi itu (lihat Aditjondro 2004a).
Jejaring korupsi Muin Pusadan berkaitan dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Poso yang juga kontraktor (warisan dari era Arief Patanga), jaringan politisi yang se daerah asal, yakni Bungku (kini di Kabupaten Morowali), jaringan alumni HMI yang telah membantu mengorbitkannya ke kursi Bupati dalam pemilihan bupati, 30 Oktober 1999 (dengan mengalihkan suara dari para pendukung calon dari PPP), jaringan pejabat Golkar di tingkat provinsi, jaringan kontraktor sebagai kolega bisnis anaknya, dan tentu saja, aparat penegak hukum (lihat Harli 2003).
Selanjutnya, marilah kita lihat oligarki yang dibangun Muin Pusadan untuk menjaga agar dana publik yang dikelolanya tidak jatuh ke orang yang jauh dari radius pengaruhnya. Suatu oligarki berlapis tiga.
Lingkaran pertama oligarki Pusadan terdiri dari anggota keluarga batihnya, saudara-saudara iparnya, serta kerabat dan kroni dari Bungku. Putra tertuanya, Muhammad Reza, adalah pemilik perusahaan kontraktor CV Sindang Laya Pratama. Berkat bantuan adiknya, Abdul Rasyid Pusadan, yang juga seorang kontraktor di Poso dan ketua Kerukunan Keluarga Bungku (KKB), diaturlah bahwa tender proyek-proyek pembangunan di Poso sering dimenangkan oleh perusahaan milik Reza atau Rasyid. Salah satu proyek yang dimenangkan oleh perusahaan keluarga Pusadan adalah proyek perbaikan teras dan plafon kantor Bupati Poso, yang rencananya akan digunakan sebagai kantor Gubernur Sulawesi Timur apabila Poso berhasil menjadi ibukota provinsi yang sedang diperjuangkan itu (Harli 2003; Fakta, Desember 2003: 33).
Lingkaran kedua oligarki Pusadan terdiri dari kerabat dan kroni Pusadan dari Bungku yang ditempatkan dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Poso. Antara lain, Amirullah Sia, saudara sepupu sekali Pusadan yang diangkat menjadi Kepala Badan Kesbang dan Linmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat), serta Asni Radi, kemanakan Pusadan yang diangkat menjadi Bendahara Kesbang dan Linmas. Dengan penempatan yang strategis ini Pusadan dapat mengatur irama pengucuran proyek dari Badan Kesbang dan Linmas (Harli 2003).
Selanjutnya, lingkaran ketiga oligarki Pusadan terdiri dari para alumni HMI yang membantu memenangkan Pusadan dalam pemilu Bupati tahun 1999. Antara lain, Haris Rengga (Infokom), Sukarti Kaleleng (Badan Pengawas Keuangan Daerah (Bawasda) Poso), Arif Latjuba (Perikanan), dan Kusmunandar Husein (Sekretaris RSU Poso) (Harli 2003).
Ketiga lingkaran oligarki Pusadan itu juga diisi oleh birokrat-birokrat yang setia padanya, dalam arti, bisa diajak bersama-sama menikmati dana-dana publik yang mereka kelola. Strategi ini sekaligus adalah untuk mengakomodasi pengelompokan etnis non-Bungku di antara para pejabat dan birokrat di Poso, agar tidak timbul oposisi terhadap dominasi Bungku dalam birokrasi Poso, sementara orang Bungku sesungguhnya sudah dapat berkiprah di kabupatennya sendiri, yakni Morowali. Apalagi sudah timbul suara-suara sinis, seolah-olah Poso sudah dikuasai oleh “PBB” – Persatuan Bungku-Bungku, mengingat bahwa Ketua DPRD Kabupaten Poso, Akram Kamarudin, juga orang Bungku.
Di antara tokoh-tokoh non-Bungku yang ditempatkan oleh Pusadan dalam birokrasi pemerintahannya itu terdapat Suryadi Ngewa, orang Ampana yang diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Poso, merangkap Pimpinan Proyek Rehabilitasi Sekolah di Ampana. Tokoh-tokoh lain adalah Johanes Tumiwa, Kepala Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) dan Mashuri Lahai, Kepala Dinas Pemukiman dan Penataan Wilayah (Kimtawil) Kabupaten Poso. Rivalitas di antara kedua tokoh yang pernah berseberangan ini diakomodir Pusadan dengan memecah Dinas Kimpraswil menjadi Dinas Praswil dan Dinas Kimtawil. Kini kedua orang itu menjadi orang yang (merasa) paling dekat dengan sang Bupati.
Tokoh lain yang juga sangat berpengaruh adalah Bahrun Latjuba, orang Tojo yang diangkat menjadi Asisten II Setkab bidang Administrasi Pembangunan. Posisi ini sangat strategis, sebab dari sinilah hampir semua proyek kesejahteraan sosial terkucur. Tokoh ini cukup kontroversial, sebab pada tahun 2002 ia pernah diperiksa polisi dalam kaitan dengan manipulasi pembagian beras miskin (raskin) yang dikelolanya. Ada indikasi bahwa sebagian beras itu dijualnya untuk membangun rumah mewah di Jl. Tanjung Bulu, Ampana. Tapi ada indikasi juga bahwa ia pernah membagikan dua ton raskin untuk operasi Lasykar Jihad di Poso, sebelum organisasi paramiliter Muslim itu dibubarkan (Harli 2003).
Bahrun Latjuba juga punya kontribusi lain dalam oligarki Pusadan: ia merupakan mata rantai antara kepentingan bisnis keluarga besar Pusadan dan keluarga besar Sekretaris Kabupaten Poso, Awad al-Amri, lewat pernikahannya dengan seorang adik Awad al-Amri.
Mengikuti jejak Muin Pusadan, sang Sekkab mengangkat sejumlah kerabat dan kroninya dalam birokrasi pemerintahan di Poso. Isterinya sendiri, dokter gigi Asnah al-Amri, diangkatnya menjadi Kepala Badan Kesehatan Poso. Andi Rahmatullah Yusuf, suami dari Yaya al-Amri yang juga seorang adik Awad, diangkatnya menjadi Kepala Dinas Catatan Sipil Poso. Iparnya yang lain, Bahrun Latjuba, diangkatnya menjadi Asisten II Setkab Poso. Seorang kerabat lain, Munir al-Amri, diangkatnya menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Poso (Harli 2003).
Berkat sinerji antara Muin Pusadan dan Awad al-Amri beserta kerabat dan kroni-kroni mereka, oligarki ini dapat mengatur penerimaan pegawai dan pengucuran proyek-proyek ke perusahaan-perusahaan keluarga mereka. Makanya tidak mengherankan bahwa BPK menemukan 51 paket proyek bernilai milyaran rupiah yang dinyatakan 100% selesai selama tahun anggaran 2001-2002, tapi kenyataannya sebagian besar tidak pernah dikerjakan atau dikerjakan secara serampangan (Harli 2003; Fakta, Desember 2003: 33).
Satu hal menarik perlu dicatat tentang siasat politik oligarki ini. Di satu fihak, Muin Pusadan juga mengakomodir sejumlah birokrat Kristen, atau yang berlatar belakang suku-suku asli Poso yang beragama Kristen. Asisten III Setkab bidang Administrasi & Keuangan, Rampu Kandolia, adalah seorang Pamona. Asisten I Setkab bidang Pemerintahan, Hari Kabi, berasal dari Lembah Napu, Kecamatan Lore Utara. Birokrat lain dari suku Lore adalah Daniel Tokare, Kepala Bagian Keuangan, yang berasal dari Lembah Bada. Sedangkan Kepala Dinas Praswil yang sudah disebut namanya tadi, Yohanes Tumiwa, berdarah Minahasa.
Tapi di fihak lain, Pusadan juga dekat dengan orang-orang yang pernah (atau masih?) mendukung kegiatan kelompok-kelompok paramiliter Muslim di Poso. Misalnya, Bahrun Latjuba yang pernah membagi dua ton raskin kepada Lasykar Jihad di Poso. Selain itu, Pusadan ditengarai memberikan rekomendasi kepada Daeng Raja, untuk menjual pakaian bekas yang disita Bea Cukai Poso dari kapal yang berangkat dari Malaysia (Fakta, Des. 2003: 33).
Seperti yang telah disinggung di depan, tokoh tua berdarah Bugis ini pernah terlibat dalam manipulasi dana KUT dan ikut memicu gelombang pertama dan kedua kerusuhan Poso, dan secara aktif mendukung kehadiran Lasykar Jihad di Poso. Namun setelah berhasil mengubah citranya dari provokator menjadi rekonsiliator, dengan ikut menandatangani Deklarasi Malino, dan duduk dalam Kelompok Kerja Deklarasi Malino (Pokja Deklama) Kabupaten Poso, Daeng Raja mendapat kepercayaan untuk membangun markas Brimob di Kelurahan Mo-engko, Poso.
Walhasil, berkat kehebatan Pusadan bersama kerabat dan kroninya memanipulasi anggaran pembangunan dan dana bantuan pengungsi, kekayaannya yang tampak kini sudah menyaingi, kalau tidak melebihi pendahulunya. Bekas PR III Universitas Tadulako itu kabarnya kini telah beternak rumah dan mobil mewah di mana-mana. Ia kabarnya memiliki tiga buah rumah pribadi di Poso. Salah satu rumah pribadi itu dibelinya dari bekas Kepala RSU Poso, dan terletak di Jalan Pulau Bali di Kelurahan Gebangrejo. Salah satu lagi terletak di Jalan Talasa, Kelurahan Lawanga, yang sebelumnya milik S. Wounde, bekas anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar, sedangkan salah satu lagi dibelinya dari Pandeleke, seorang bekas birokrat senior. Rumah besar itu terletak di samping Hotel Wisata di Kelurahan Lawanga.
Transaksi rumah di Jalan Pulau Bali itu dilakukan oleh Wani Lamusu. Anak dari Nani Lamusu, seorang pengusaha ikan kelas kakap yang berdarah Gorontalo itu tampaknya merupakan orang kepercayaan sang Bupati untuk urusan bisnis pribadinya. Wani Lamusu sendiri seorang kontraktor.
Selanjutnya, sang Bupati memiliki enam rumah pribadi di kota Palu. Satu di Jalan Teluk Tomini No. 9A, di Jalan Tanjung Satu No. 81, di Jalan Tanjung Satu, di Jalan Tanjung Balantak, dan di Jalan Nuri. Sedangkan rumah pribadi yang keenam adalah bekas rumah dinasnya di Kompleks Perumahan Dosen Universitas Tadulako di Jalan Slamet Riyadi (Koran Akses, Minggu III Maret 2004 & Minggu II April 2004).
Di luar Sulawesi Tengah, keluarga Pusadan masih memiliki satu rumah pribadi di Kompleks Panakukkang, Makassar, yang dilengkapi dua buah mobil mewah, satu rumah mewah di Depok, Jakarta Selatan (no telp: 021 787 0484), Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Bandung.
Semua transaksi rumah mewah Pusadan di Palu dilakukan oleh adik iparnya, Ibrahim Rauf yang akrab dipanggil Ingo, yang tinggal di samping rumah di Jalan Tanjung Satu yang sedang direnovasi. Salah satu rumah di Jalan Tanjung Satu punya tanah pekarangan seluas satu hektar, yang rencananya mau dibangun jadi RS swasta. Salah satu rumah di Jalan Tanjung Satu sudah direnovasi oleh Abun, salah seorang direktur CV Tri Candra, dengan biaya Rp 270 juta. Harga belinya Rp 400 juta. Rumah itu sekarang dijadikan klinik dengan dilengkapi delapan buah AC, satu set alat-alat medis. Sedangkan yang satu sekarang (5 April 2004) sedang direnovasi oleh Abun, sekaligus pemagaran di sekeliling tanah seluas satu hektar itu.
Rumah di Jalan Balantak sedang direhabilitasi oleh orang yang sama, begitu pula rumah yang di Jalan Nuri. Rumah tersebut dibeli Pusadan dari Ir. Bagio, mantan pimpinan proyek Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, senilai Rp 400 juta. Begitu pula rumah yang di Jalan Teluk Tomini itu, menurut satu sumber. Juga dibeli dari Ir. Bagio, sekitar dua tahun lalu. Menurut sumber itu, di rumah di Teluk Tomini itulah Muin Pusadan dan keluarganya menginap, jika sedang berada di Palu. Tapi ketika diwawancarai oleh Koran Akses, Minggu III Maret 2004, Muin Pusadan mengatakan bahwa rumah di Teluk Tomini hanya dia kontrak dari Ir. Bagio, karena rumahnya sendiri di Palu sedang direnovasi.
Adapun salah satu rumah di Jalan Tanjung Satu itu, menurut Muin Pusadan lagi, bukan miliknya, melainkan milik yayasan keluarganya yang dipimpin oleh Dokter Rudy. Nama yayasan itu dia tidak ingat, “pokoknya Dokter Rudy yang tahu, katanya kepada Koran Akses , edisi Minggu III Maret 2004. Dokter Rudy Rauf ini memang adik ipar sang bupati, yang beristerikan Ramlah Rauf. Bekas Kepala RSU di Buol-Toli-toli ini, juga mendapat order dari Pemerintah Daerah Poso, berupa pengadaan alat-alat kesehatan senilai Rp 1 milyar. Sedangkan yayasan keluarga yang dipimpin oleh sang dokter ini, baru didirikan beberapa minggu lalu, setelah kekayaan dan dugaan korupsi sang bupati mulai dibeberkan di media massa. Begitu menurut seorang narasumber di Poso. Sedangkan rumah di Jalan Balantak itu diakuinya bukan miliknya, melainkan milik anaknya, dan bukan sedang direnovasi, tapi hanya sedang diperbarui catnya. Begitu kata sang Bupati pada Koran Akses, Minggu III Maret 2004.
Hampir setiap rumah pribadi itu dilengkapi dengan sebuah mobil mewah. Di Jalan Teluk Tomini No. 9A, Palu, diparkir dua buah mobil Nissan Terano dengan nomor polisi DN 557 AF dan DN 6001 AF, yang masing-masing ditaksir harganya Rp 400 juta, sementara di rumahnya di Bandung diparkir sebuah BMW senilai Rp 600 juta. Rumah-rumah dan mobil-mobil mewah di Jawa itu diperuntukkan bagi anak-anak serta kerabat Pusadan yang bersekolah atau bertugas di sana.
Di (kota) Poso dan Palu sendiri, ada beberapa proyek yang diduga di mark-up oleh sang Bupati atau anak buahnya. Proyek-proyek mercu suar itu adalah Mess Pemda Kabupaten Poso yang mewah dengan 25 kamar Jalan Sam Ratulangie, Palu, yang anggarannya Rp 5,1 milyar, yang baru diresmikan oleh sang Bupati hari Sabtu, 13 Maret lalu (Poso Post, 26 Maret – 10 April 2004); rehabilitasi Kantor Bupati Poso senilai Rp 6 milyar; serta pembangunan sebuah gedung RSU berlantai tiga dengan anggaran Rp 9,8 milyar.
Mungkin karena ingin mendekati para mahasiswa asal Poso di Jawa dan di Makassar, untuk memuluskan masa jabatannya yang kedua, baru-baru ini Muin Pusadan mengadakan serangkaian pertemuan dengan mereka. Di Yogya, pertemuan pertama dilakukan hari Senin, 29 Maret 2004, bertempat di Asrama Sulteng, dihadiri 16 orang mahasiswa. Pertemuan kedua, hari Selasa, 30 Maret 2004, diselenggarakan di Restoran Pringsewu, yang dihadiri sekitar 30 orang mahasiswa. Dalam pertemuan pertama, anggaran makan malam sebanyak Rp 400 ribu, dibagi-bagikan kepada setiap peserta masing-masing Rp 25 ribu. Sedangkan dalam pertemuan kedua, makan malam ditraktir oleh Pusadan.
Dalam pertemuan kedua itu “disepakati” bahwa Bupati akan membeli tanah untuk membangun gedung asrama mahasiswa Poso, berlokasi dekat asrama mahasiswa Sulteng, dengan anggaran Rp 500 juta. Uang sebanyak itu sudah diantarkan sendiri oleh Asisten III Kabupaten Poso, Rampu Kandolia, ke kalangan mahasiswa Poso di Yogyakarta. Tidak jelas apakah dana itu dikeluarkan dari kas daerah atas persetujuan DPRD Poso, hasil mark up proyek-proyek yang ditangani oleh Pemda Poso, atau hasil korupsi oligarki Pusadan sendiri.
Diteladani oleh Bupatinya sendiri, di tingkat kelurahan juga terjadi korupsi besar-besaran dari dana bantuan buat pengungsi dan para korban konflik lainnya, misalnya di Kelurahan Kayamanya, Poso Kota. Sebelum kerusuhan penduduk kelurahan itu tercatat sekitar 1600 keluarga, hampir 10% di antaranya beragama Kristen dan sudah hijrah ke Tentena, Palu, dan Minahasa. Tapi ketika mengambil jatah jadupnya, September lalu, seorang narasumber menyaksikan bahwa jumlah penduduk Kelurahan itu sudah berlipatganda menjadi lebih dari 4000 keluarga.
Gejala itu tidak cuma terjadi di Kayamanya. Telah diakui sendiri oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulteng, Andi Asikin Suyuti, bahwa ada sejumlah kelurahan dan desa mengusulkan pengungsi yang sudah menerima bantuan jadup dan bedup dan yang hanya mengaku sebagai pengungsi, sehingga terjadi “penggelembungan pengungsi” sampai 20 ribu keluarga (Fajar, 12 Agustus 2003).
Sementara itu, di kota Tentena di tepi Danau Poso, masih ada ribuan pengungsi yang belum pernah menerima jadup maupun bahan bangunan rumah (BBR). Atau ada juga yang baru menerima jadup tahun lalu, tapi dipotong Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhitung sejak empat tahun lalu. Padahal, rumah mereka sudah terbakar sejak kerusuhan tahun 1998 – 2000.
(c ). Investor-investor besar, yang sudah atau akan terlibat dalam usaha-usaha pengelolaan sumber-sumber daya alam di daerah Sulawesi Tengah bagian Timur, yang punya potensi penggusuran yang besar:
Investor-investor besar ini, juga berpotensi menikmati keuntungan akibat kerusuhan yang terus dilestarikan di Kabupaten Poso dan tetangga-tetangganya di timur. Keuntungan mereka adalah dalam dua hal. Pertama adalah jatuhnya harga tanah di daerah kerusuhan, dan kedua adalah pengamanan langkah-langkah penggusuran rakyat setempat oleh aparat keamanan yang semakin bertambah di daerah-daerah konflik maupun yang terkena imbasnya.
Seperti yang telah disinggung di depan, dua investor terbesar di Sulteng bagian Timur adalah pertama, kelompok Medco, yang melalui JOB Pertamina – PT Exspan Tomori Sulawesi sedang melakukan eksplorasi migas di wilayah yang terentang dari terumbu karang Tiaka di Teluk Tolo s/d Kecamatan Toili dan Batui di Kabupaten Banggai; kedua, kelompok Artha Graha, yang punya rencana membuka tambang marmer seluas 150 hektar di Kabupaten Morowali (selengkapnya lihat tulisan Nerlian Gogali dalam buku ini).
APA YANG HARUS DILAKUKAN?
(a). Menolak penetapan status darurat sipil bagi daerah Poso dan Morowali.
(b). Secara konsepsional, mulai membedakan militer (TNI) dan polisi, baik institusinya maupun tugas dan cara operasionalnya, sehingga masyarakat luas tidak lagi selalu menganggap kedua kekuatan bersenjata itu mempunyai fungsi yang sama. Dalam sebuah negara yang demokratis dan menganut supremasi sipil, polisi adalah bagian dari pemerintah sipil, berada di bawah komando kepala-kepala daerah, dan tugasnya adalah menegakkan keamanan dalam negeri (internal security ). Sedangkan militer berada di bawah komando Presiden sebagai Kepala Negara, dan hanya bertugas mempertahankan negara dari serbuah musuh, tanpa diembel-embeli fungsi-fungsi politik dan ekonomi, seperti yang sekarang masih kita lihat di negara kita.
(c). Menarik pasukan-pasukan TNI/Angkatan Darat dan Brimob dari daerah Sulawesi Tengah bagian Timur, baik pasukan yang beroperasi secara terbuka, maupun pasukan-pasukan yang beroperasi secara terselubung.
(d). Memprioritaskan pemanfaatan tenaga Polisi untuk pengamanan di daerah kerusuhan, dengan meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi gejolak, unjuk rasa, dan bentuk-bentuk kerusuhan sosial lainnya dengan teknik pengendalian huru hara tanpa membunuh.
(e). Menggalakkan pendekatan antara calon penanam modal dengan rakyat setempat dengan menghormati hak-hak rakyat – baik penduduk asli, petani pendatang (transmigran), penduduk di kawasan pemukiman setempat, maupun buruh — , tanpa pendekatan keamanan, yakni menakut-nakuti rakyat dengan intervensi militer berupa latihan perang-perangan, unjuk kekuatan fisik (show of force ) yang selama ini dilakukan di Sulawesi Tengah bagian Timur, khususnya di Kabupaten Banggai.
Palu, 10 Februari 2004.
Kepustakaan:
Aditjondro, G.J. (2001). “Guns, Pamphlets and Handie-Talkies: How the Military Exploited Local Ethno-Religious Tensions in Maluku to Preserve their Political and Economic Privileges.” Dalam Ingrid Wessel & Georgia Wimhoefer (peny.). Violence in Indonesia. Hamburg: Abera, hal. 100-128.
————— (2003). “Renungan buat Papa Nanda, Anak Domba Paskah dari Tentena”. Prolog untuk Rinaldy Damanik. Tragedi Kemanusiaan Poso: Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam. Jakarta & Palu: PBHI & LPS-HAM Sulteng.
————— (2004a). Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia: Investigasi Korupsi Sistemik Bagi Aktivis dan Wartawan. Jakarta & Kendari: LSPP, PSHK & Formas.
————— (2004b). “Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi bagian Timur”. Jurnal Wawasan, INSIST, Yogyakarta, edisi mendatang.
Damanik, Rinaldy (2003). Tragedi Kemanusiaan Poso: Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam. Jakarta & Palu: PBHI & LPS-HAM Sulteng.
Harli (2003). Keuntungan di Balik Tragedi Kemanusiaan di Poso. Draft untuk buku tentang Tragedi Kemanusiaan di Poso dan Morowali yang sedang dipersiapkan di Palu.
ICG (2002). Indioonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates. Asia Report No. 43. Jakarta/Brussels: International Crisis Group.
Pode, Prama’artha S.L. (2003). Ambo Dae: Binatang Apakah itu? Makalah tak diterbitkan. Yogyakarta.
Pokja RKP (2003). Laporan Akhir Tahun 2003: Lima Tahun Konflik Poso, Dua Tahun Deklarasi Malino: 2003, Darah Masih Tumpah, 2004, Masa Pemulihan Kepercayaan (Trust Building ). Palu: Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Porka RKP).
Sondeng, Usman (2001). Menggali Akar Permasalahan Kasus Poso dan Formulasi Cara Penyelesaiannya, dengan Suplemen I & II. Palu.
Tengko, Rafyudin (t.t.) Pertikaian Poso dalam Tataran Realitas: Sebuah Catatan dari Pengalaman Lapangan. Naskah yang tidak diterbitkan.
[1] ) Ironisnya, seusai konflik antara Bupati dan Dandim Poso itu, setelah Usman Sondeng kembali ke Poso, anggota BPH Bidang Ekonomi itu sendiri berurusan dengan aparat hokum karena dituduh korupsi tekstil, diadili dan dipenjara.
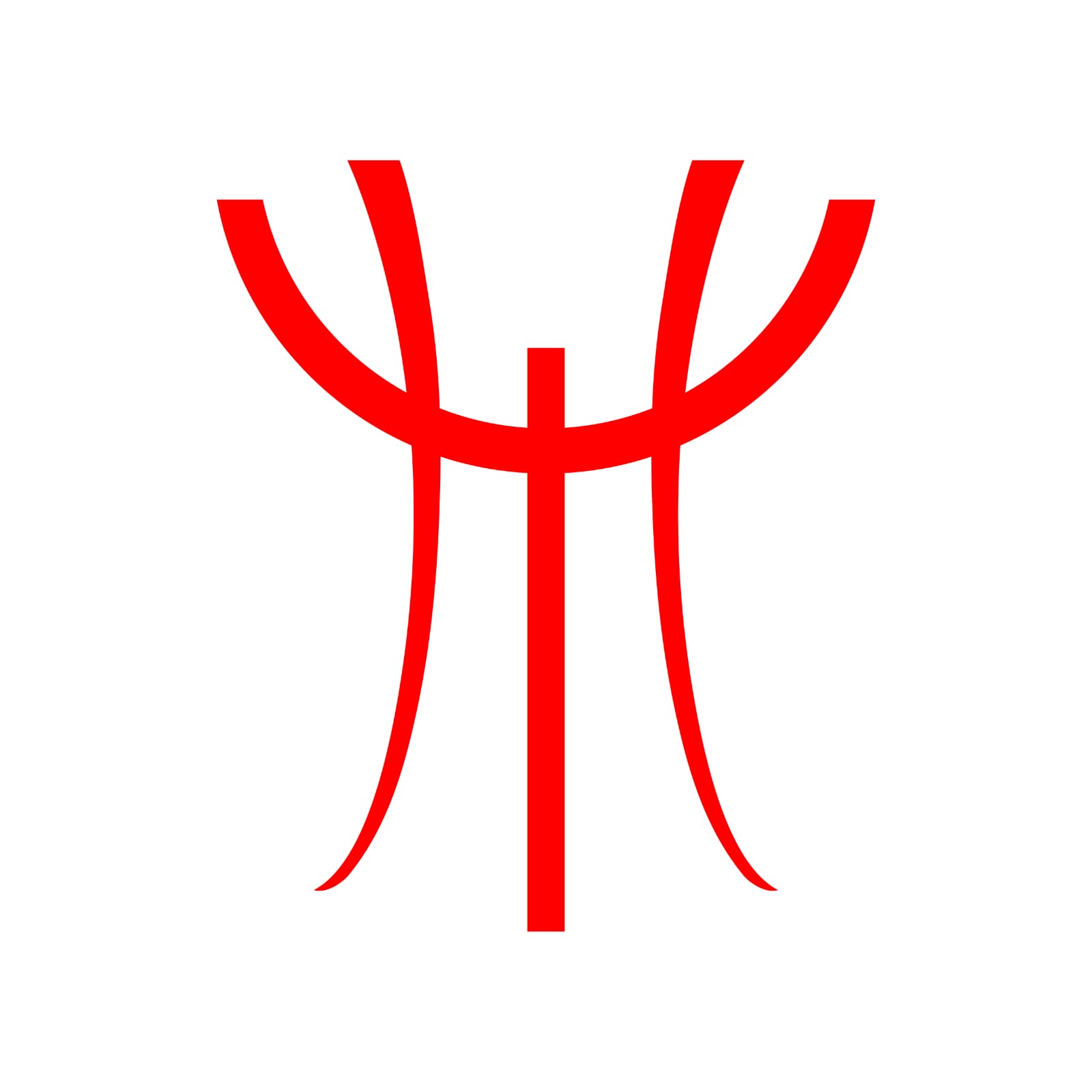

Tinggalkan Balasan